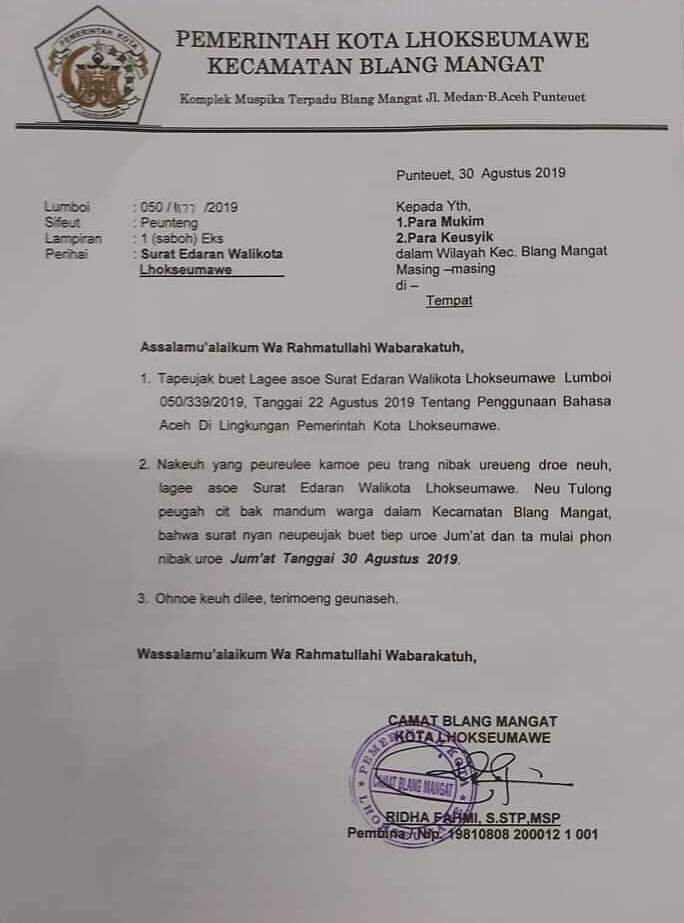BERDASARKAN penelitian dari beberapa sumber sejarah, Bahasa Aceh (BA) dipercayai hanya berada pada tingkatan oral saja. Pernyataan ini didukung oleh penemuan-penemuan mengenai sedikitnya dokumen-dokumen sejarah BA sebagaimana Prof. Dr. Yusni Saby mengutarakan bahwa sumber-sumber tersebut tidak lengkap dan issufficient. (Saby, 2001: 5).
Ada beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kealpaan dokumen dalam BA. Di antaranya, peristiwa Pembakaran Dayah Tanoh Abee oleh Kolonialis Belanda yang terjadi pada masa kepemimpinan Teungku Muhammad Ali al-Bagdadi (1861-1969). Ketika Belanda berhasil mengontrol Keraton Aceh, Beliau telah memperkirakan bahwa Belanda akan segera menyerang Seulimeum.
Oleh karena itu, Beliau memindahkan 10.000 buku-buku di Dayah Tanoh Abee ke tempat-tempat yang diperkirakan aman, termasuk ke dalam gua di sekitar Desa Teureubeh, Jantho, sebelum Belanda menyerang Seulimeum dan membakar Dayah Tanoh Abee. Setelah 5 tahun naskah-naskah yang kemudian berhasil dikumpulkan sebagian besar ditemukan dalam kondisi rusak. Naskah utuh yang diperoleh hanyalah berkisar 2.000 saja (Hasjmy, 1997: 3-10).
Kemungkinan lainnya adalah peristiwa pembakaran Masjid Raya Baiturrahman pada 1677 M yang berlangsung selama pemerintahan Sultanah Nur Alam Naqiyatuddin Syah (1676-1678). Baiturrahman merupakan satu-satunya sumber unik karena memiliki berbagai variasi kitab, baik buatan ulama lokal maupun asing. Buku-buku tersebut diperkirakan dibawa dari luar negeri seperti Arab, India, dan mungkin juga Persia, seiring dengan kedatangan ulama-ulama asing yang mengajar di Aceh. Salah satu contohnya, kitab Tajussalatin dikarang di Persia oleh seorang pedagang dari Bukhara dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di Aceh pada 1603 M (Winstedt, 1969; 137).
Begitu juga dengan sumber-sumber yang ditulis sebelum masa Hamzah Fansuri dapat dikatakan berada di pustaka tersebut, karena islamisasi di Aceh sudah dimulai sejak abad ke-8 M dan telah melahirkan Zawiyah pertama di Asia Tenggara. Disamping itu, fakta Portugis menaklukan Melaka pada tahun 1511 M menyebabkan pelarian-pelarian pedagang dalam jumlah besar, termasuk ulama yang kemudian menjadi pengajar di Aceh. Jadi, secara logis, bagaimana ulama-ulama tersebut tidak melahirkan satu karya pun atau membawa beberapa buku pedoman sebagai pegangan bagi mereka yang sedang belajar Islam selama proses misionaris tersebut.
Kepopuleran Syeikh Nuruddin Ar-Raniri yang melahirkan tulisan-tulisannya dengan mengambil contoh prototype dari Sejarah Melayu (1612) merupakan salah satu realita pendukung ilmiah yang jelas. Lebih jauh lagi, sebagaimana halnya yang terjadi di negeri-negeri Islam, ketika negeri tersebut mencapai puncak kejayaannya, perhatian terhadap karya-karya ilmiah semakin meningkat.
Begitu juga dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Merupakan hal yang mustahil jika Sultan Iskandar Muda tidak berupaya membentuk sebuah perpustakaan, apalagi Baiturrahman saat itu memiliki berbagai tingkatan pendidikan, termasuk pendidikan tingkat tinggi atau universitas dimana astronomi, metafisika, matematik, dan politik ikut dipelajari disamping pelajaran-pelajaran keagamaan seperti tauhid, fikih,dan lain sebagainya (Auni, 1993:84).
Selain itu, laporan-laporan tentang Aceh yang dibuat oleh Belanda selama masa penjajahan dan dikirim ke Batavia hampir tak pernah disebutkan oleh para peneliti hingga hari ini. Laporan-laporan yang dipercaya mengendap di Leiden tersebut diperkirakan memiliki data-data detail tentang politik, sosial, dan budaya, termasuk BA mengingat perkembangan yang terjadi selama masa kolonialisme berputar pada pergolakan implementasi BA Kutaraja sebagai bahasa utama yang dipedomankan pada sekolah-sekolah kolonialis di Aceh.
Meskipun BA barangkali tidak dikenal dalam aspek administratif, berdasarkan hasil penelitian arkeologi, BA tercatat tidak hanya dalam penulisan-penulisan sastra seperti sajak tapi juga pada batu-batu nisan. Contohnya, Batu Nisan Ratu Al’ala (14 Zulhijah 781/1388 M) yang menguasai kesultanan Pasai dan Kedah di Minye Tujoh, Matang Kuli (Sulaiman, 1977:3). BA juga ditemukan dalam dokumen-dokumen keagamaan dan bidang-bidang keilmuan pada abad ke-18 hingga abad ke-20 (Usman, 2003:32).
Seiring dengan perjalanan waktu, Belanda yang menjajah Aceh dan berhasil menduduki keraton telah melakukan berbagai perubahan dalam sistem penggunaan BA. Salah satunya adalah mengesahkan BA Kuta Raja sebagai bahasa beradab. Perubahan tersebut kemudian terimplementasi di sekolah-sekolah Kolonialis di Aceh dan menjadi media komunikasi antar-pemerintah.
Melalui seminar Bahasa Aceh yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Pembinaan Pengajaran Bahasa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung Cabang Banda Aceh pada tahun 1990-an, diketahui bahwa BA Kutaraja ini kemudian dikenal dengan nama Standaart Atjehsch. (nn, tt:3). Perubahan-perubahan tertentu terjadi dalam politik di Aceh melalui intervensinya dalam BA seperti, mengganti ejaan BA yang awalnya dalam bahasa/tulisan Djawi dengan ejaan Latin (atau Romawi) agar mudah dipelajari oleh pihak Belanda sekaligus dapat mengubah paradigma sosial agama anak-anak Aceh yang dididik di sekolah ‘binaan’ mereka.
Buah usaha tersebut adalah terbitnya buku-buku berbahasa Aceh dengan gubahan latin seperti, buku karangan Mohammad Djam dan Nya’ Cut yang dipedomankan di sekolah Voolkschool. Di antaranya; Doea Seulajeu, Batjut Sapeu. Setelah itu menyusul beberapa buku lain seperti Bidjeh I, II, oleh Abu Bakar and M. Saleh (1929), Lhee Saboh Nang I, II, dan III dengan pengarangnya L. D. Vries and H. Abu Bakar (1931-1932), Meutia I dan II sebagai lanjutan dari Lhee Saboh Nang dan Bungong Situngkoj, Oleh Teungku Muhammad Noerdin. Hingga hari ini buku-buku tersebut tergolong sulit untuk ditemukan.
Kini, penemuan-penemuan tentang adanya penurunan pemakai BA menggelitik benak kita untuk bertanya, apakah BA yang dipercayai memiliki tempat penting dalam sejarah akhirnya pupus? Atau akan terus berada dalam baris komunikasi oral? Sungguh amat disayangkan jika bahasa yang tergolong tua ini perlahan-lahan tergeser dan identitas kita sebagai orang Aceh secara otomatis juga tergantikan dengan identitas yang abracadabra.
Sungguh saya tidak mengetahui sudah berapa banyak panggilan yang disampaikan pada pemerintah kita untuk membantu terwujudnya akses pelestarian bahasa daerah yang hingga hari ini belum menampakkan gerakan tertentu. Tentu panggilan tersebut tidak hanya untuk pemerintah kita saja, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Aceh, dari barat, timur, utara, dan selatan, meskipun kita memiliki budaya dan bahasa yang beragam. Marilah kita jadikan bahasa Aceh menjadi bahasa pemersatu kita semua.
Sumber : atjehpost.com