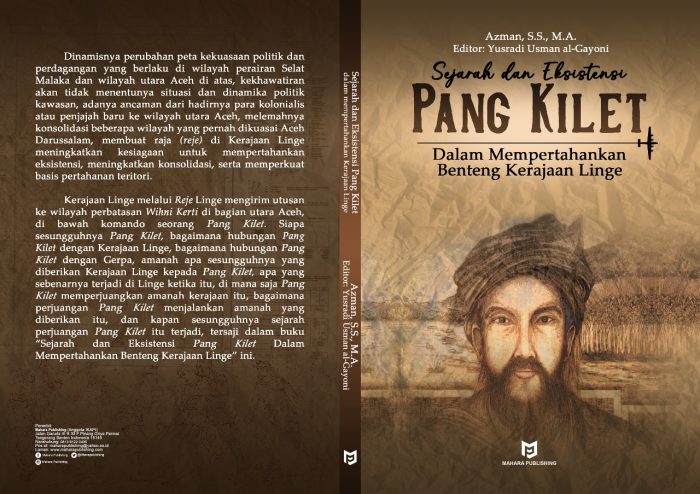Oleh. Drs. Jamhuri, MA*
DUA sistem kekerabatan yang dikenal dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu fitrilineal atau fatriarkhi dan matrilineal. Fatrilineal atau juga sering disebut dengan Fatriarkhat sering disamakan, kendati keduanya sebenarnya berbeda, yang satunya berarti menarik garis keturunan melalui ayah dan satunya lagi adalah kekuasaan yang berada di tangan laki-laki. Sedang matrilineal adalah panarikan garis keturunan melalui pihak perempuan atau ibu dan sitem teralhir ini dianut tidak sebanyak sistem fatrilineal atau farental.
Masyarakat dimana turunnya al-Qur’an (Mekkah dan Madinah) menganut sistem kekerabatan fatrilineal sehingga yang bertanggung jawab dalam masyarakat dan keluarga adalah kaum laki-laki, mereka yang berkewajiban memenuhi kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga, mereka juga yang boleh menjadi penguasa dalam ruang publik dan juga domistik. Perempuan tidak punya kewajiban bahkan tidak punya hak untuk menjadi penanggungjawab kebutuhan dalam rumah tangga, perempuan juga tidak punya kewajiban dan hak untuk menjadi penguasa.
Karena kekuasaan berada di tangan kaum laki-laki, maka kesewenangan dalam menggunakan kekuasaan sering terjadi. Seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pembiaran terhadap perempuan yang hamil di luar nikah dan penelantaran anak setelah perceraian. Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga sering terjadi di negara-negara maju walaupun jumlah prosentasenya berbeda.
Kedua sistem kekerabatan yang telah disebutkan berjalan di beberapa belahan dunia, namum kekerabatan fatrilineal lebih mendominasi. Kedua kekrabatan ini belum mengalami perubahan kendati kemajuan peradaban manusia telah menghendaki adanya perubahan.
Ide dasar pewahyuan al-Qur’an adalah merobah secara total budaya masyarakat Arab jahiliyah karena tidak sesuai dengan hukum dan kehendak Tuhan yang maha Bijaksana dan maha Mengetahui, namun ide itu belum terlaksana secara sempurna disebabkan pola pemahaman yang melekat pada masyarakat itu masih terpaku dengan pola budaya yang berlaku sejak masa sebelum turunnya al-Qur’an. Untuk hal ini kita sebutkan satu contoh, dimana pada masa awal, lebih-lebih pada masa jahiliyah atau masa sebelumnya ketika masyarakat tidak berakhlak kesewenangan yang tanpa batas berlaku, di sisi lain kondisi alam pada masa itu juga tidak memungkinkan kaum perempuan untuk melakukan aktifitas sama dengan laki-laki, pola pemahaman yang masih mengandalkan kekuatan fisik berlaku dalam masyarakat, mereka yang lemah (tidak memiliki kekuatan fisik) termasuk laki-lak akan tertindas.
Pemahaman dan pelaksanaan aktifitas kehidupan yang mengandalkan fisik berlangsung lama bahkan sampai saat ini masih terlihat. Bila hal in masih tetap berjalan dalam masyarakat maka penindasan terhadap yang lemah masih tetap berjalan, namun kita tidak bisa menafikan perkembangan dunia saat ini telah melihat bahwa sebenarnya kekuasaan itu tidak lagi berada pada kekuatan fisik tetapi telah berpindah kepada pengandalan kecerdasan intelektual.
Pergeseran pemahaman dari makna kekuasaan yang berada pada fisik kepada kecerdasan intlektual, berpengaruh kepada seluruh segi kehidupan manusia. Diantaranya adalah sebelumnya semua orang berkeyakinan bahwa mereka yang sanggup memberi nafkah kepada keluarga adalah kaum laki-laki dan tidak memerlukan bantuan pihak lain (perempuan), namun ketika zaman memeberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk berbuat ternyata juga bisa.Malah pada saat persaingan bukan lagi pada tataran fisik banyak kaum perempuan lebih unggul dari kaum laki-laki, banyak kaum perempuan yang mendapat kesempatan bekerja baik di pemerintahan atau juga swasta dan sebaliknya banyak kaum laki-laki tidak mendapatkan kesempatan bekerja. Sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga yang dipahami berada di tangan laki-laki berpindak kepada perempuan.
Praktek seperti ini diakui dan diketahui oleh semua orang, namun karena ideologi awal bahwa kekuasaandan kekuatan ada pada fisik yang dimiliki oleh laki-laki, maka laki-lakilah yang berkuasa. Kakuatan ideologi ini ditambah lagi dengan pemahaman terhadap teks al-Qur’an yang tidak pernah boleh berubah, seperti pemahaman pada pernyataan Allah “Wa ‘alal mauludi lahu rizkuhunna wa kiswatuhunna”. Yang memberi makna bahwa anak adalah milik ayah atau anak dinasabkan kepada ayah, ayah juga berfungsi sebagai suami yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada para isteri.
Ayat ini dipahami oleh Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali (jumhur ulama) nasab anak kepada ayah dan nafkah menjadi kewajiban suami yang tidak boleh beralih kepada orang lain termasuk isteri, sehingga apabila suami tidak sanggup memberinya nafkah kepada para isteri maka para isteri boleh meminta cerai (fasakh) dari suaminya. Sedang menurut mazhab Zhahiri apabila suami tidak sanggup menafkahi para isteri, maka kewajiban berada di tangan isteri dan isteri tidak boleh meminta cerai dari suaminya.
Kedua pemahaman ini masih bisa kita kembalikan kepada dua pola kekerabatan di atas, artinya Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali masih memahami sistem kekerabatan secara ketat dengan tidak melihat kondisi lain yang muncul kemudian. Pemahaman Zhahiri juga belum lepas dari sistem kekerabatan fatrilineal karena beliau berpendapat bahwa kewajiban nafkah terhadap para isteri tidak berpindah kepada isteri atau orang lain semasih suami mempunyai kemampuan dan baru berpindah apabila suami tidak mampu.
Pemahaman jumhur ulama di atas selajutnya memberi pemahaman kepada kita, bahwa harta yang didapat isteri tidak harus diberikan kepada keluarga sebagai belanja, tetapi kalaupun itu diberikan hanyalah merupakan wujud dari bantuan atau kebaikan para isteri. Dalam kondisi suami mempunyai kemampuan, pendapat jumhur dan Zhahiri sama yaitu harta yang didapat isteri yang diberikan kepada keluarga posisinya sebagai kebaikan, sedangkan ketika suami tidak sanggup maka menurut jumhur tetap sebagai kebaikan dan menurut Zhahiri sebagai kewajiban.
Pemahaman lain dari ayat di atas, ketika perempuan mempunyai peluang bekerja sama dengan laki-laki, dan peluang tidak sanggupnya dalam memberi nafkan suami sama dengan ketidak sanggupan isteri dan sebaliknya peluang kesanggupannya juga sama, maka sebenarnyalah kewajiban nafkah itu berada pada keduanya yaitu suami dan isteri sebagai kewajiban bersama.