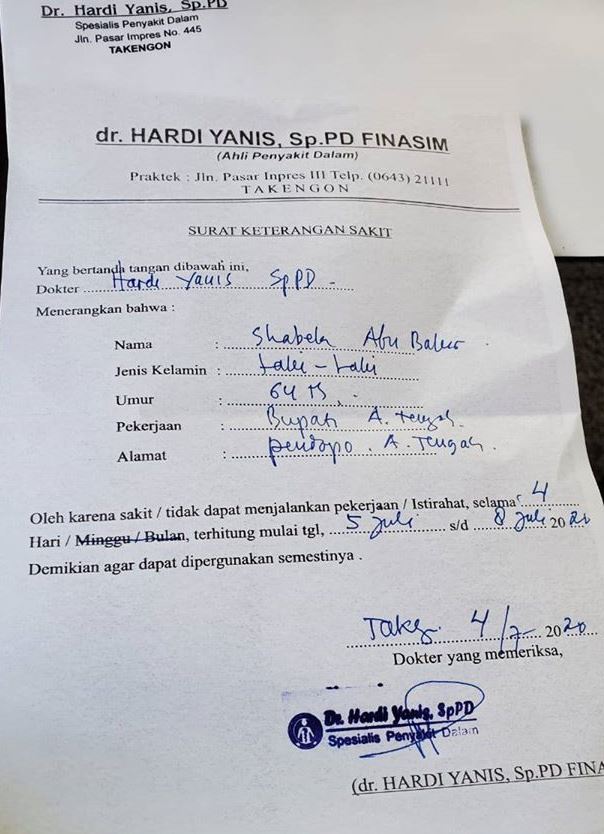Agen membangun komunikasi dua pihak, mengukur keuntungan meminimalisir kerugian. HDC dan CMI sebagai agen perdamaian telah berhasil meletakkan pondasi perdamaian Aceh. Rakyat Aceh sendiri kini harus menjadi agen untuk merancang bangunan konstruktif di atas pondasi tersebut.
Setiap celah yang ditinggalkan Henry Dunant Centre (HDC) dan Crisis Management Initiative (CMI) di pondasi itu harus dicor kembali untuk membentuk perdamaian yang hakiki di Aceh. Lubang itu masih terbuka ketika Pemerintah Pusat hingga kini belum merealisasikan turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang diamanatkan perjanjian damai, Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.
MoU bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Lihatlah kebelakang bagaimana perdamaian itu dengan susah payah diwujudkan. Ketika Aceh dan Jakarta masih kontra dalam gejolak perang. Dengan sekian ribu militer yang dikirim ke Aceh,pemerintah pusat tak kuasa meredam amarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk membentuk sebuah negara tersendiri.
Desing peluru dan dentuman bom hanya membuat GAM semakin kuat. Biaya perang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tidaklah sedikit, ribuan nyawa melayang sia-sia, setiap hari masyarakat sipil terus saja menjadi korban, dan terus bertambah dalam deretan angka-angka, tiga bahkan empat digit.
Untuk menghentikan semua itu, GAM dan pemerintah Indonesia harus ditarik ke meja perundingan. Masalahnya, para pihak punya ragam versi jalan damai yang kadang saling berbenturan. Bila itu tidak dapat disederhanakan, maka ruang yang telah dibuka tak akan pernah bisa ditempa untuk mengecor pondasi perdamaian yang diharapkan. Pada tahap inilah agen dibutuhkan.
Namun, menentukan agen yang diterima kedua pihak bukanlah perkara mudah. Militansi GAM yang telah diuji dalam 30 tahun perang tak bisa disederhanakan begitu saja. Persoalan Aceh tak lagi persoalan dalam negeri, sesuatu yang selalu ditekankan oleh pemerintah Indonesia, tapi isu kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM) telah menyeretnya menjadi persoalan di luar batas kenegerian. Nasionalisme Indonesia sudah lesu di Aceh, setelah GAM mampu membangkitkan nasionalisme keacehan yang begitu menyentak ruang negara kesatuan.
Sikap pemerintah Indonesia berubah ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Ia bersedia membuka jalan dialog dengan GAM, serta menyetujui adanya “agen” untuk misi perdamaian. Agen yang dinantikan untuk mengecor pondasi perdamaian itu kemudian muncul yakni HDC sebuah lembaga kemanusiaan yang bermarkas di Swiss. HDC secara intens membangun komunikasi dengan pimpinan GAM di Swedia dan pemerintah Indonesia di jakarta.
Saat itu meski GAM belum menaruh kepercayaan kepada pemerintah, namun mereka menyambut baik dan mau berpartisipasi dalam negosiasi. Keberhasilan pertama HDC dalam meredam konflik Aceh terwujud dengan diterapkannya Jeda Kemanusiaan di Aceh. GAM dan RI berhenti berperang untuk memberi ruang bagi masyarakat sipil memperoleh bantuan kemanusian. Pada saat itu jumlah pengungsi di Aceh sudah mencapai ratusan ribu jiwa.
Penandatangan kesepakatan Jeda Kemanusiaan dilakukan di Bavois, Swiss oleh Hasan Wirayudha duta besar RI atas nama pemerintah Indonesia dan dr Zaini Abdullah atas nama pimpinan GAM. Jeda kemanusiaan ini dilakukan selama tiga bulan dan mulai efektif berlaku sejak 2 Juni 2000.
Namun, Aceh yang sudah bertikai dengan Jakarta lebih dari tiga dekade, tidaklah bisa didamaikan dengan serta merta begitu saja. Perang terjadi lagi dengan berbagai dalih dan alasan pembenaran dari masing-masing pihak, korban masyarakat sipil terus berjatuhan.
Perubahan konstilasi politik di Indonesia juga memengaruhi menjalarnya kembali perang di berbagai daerah di Aceh. Pada masa itu Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur digoyang, saat itu pula kekerasan bersenjata di Aceh meningkat.
Lika-liku jalan terjal menuju perdamaian Aceh itu harus menjadi cerminan dan pelajaran bagi masyarakat Aceh sekarang, bahwa Aceh didamaikan di atas kubangan darah dan air mata. Merusak perdamaian ini merupakan sebuah kerugian besar, bukan hanya untuk masyarakat Aceh sekarang, tapi masa depan generasi Aceh selanjutnya. Kewajiban kita semua untuk memastikan bahwa damai ini tetap langgeng sepanjang masa.
Ketika Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan dan diganti dengan Megawati Soekarno Putri, jalan damai Aceh jadi buntu. Opsi militer yang diambil Megawati melalui penerapan Darurat Militer (DM) di Aceh membuat darah masyarakat Aceh kembali tumpah. Pada periode ini darah yang tumpah lebih banyak dari sebelumnya.
Tak ada masyarakat Aceh yang tak paham dengan kepedihan pada masa DM itu. Aceh menjadi wilayah yang sangat mencekam. Sesuatu yang harus terus kita ingat, bukan untuk kembali ke masa tersebut, tapi untuk kita renungkan dan hayati bahwa masa kelam itu harus menjadi sejarah yang tak boleh terulang. Karena itu, mari terus merawat Aceh yang damai. [Par]