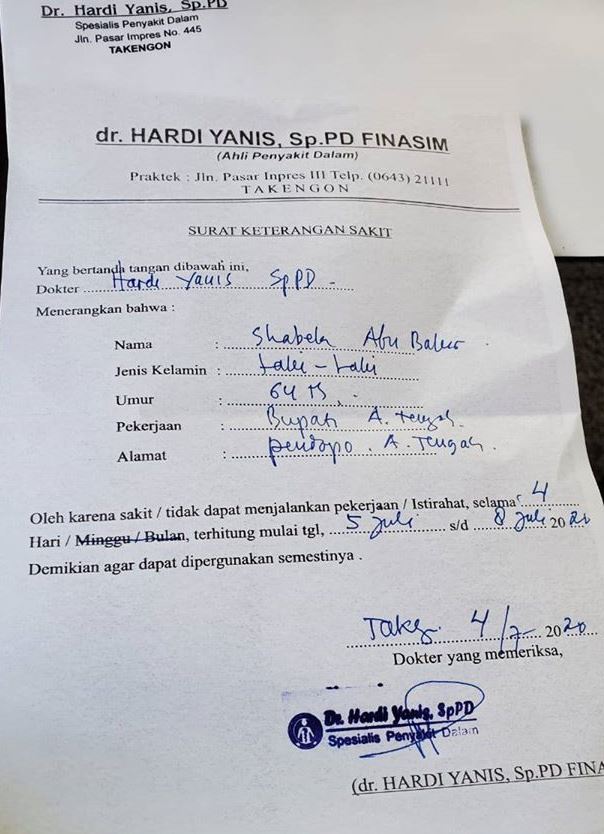Idiom Aceh memang mengatakan pat ujeuén nyang hana pirang? Pat prang yang hana reuda?. Masyarakat Aceh begitu optimis selama apa pun perang pasti ada akhirnya. Namun, butuh jiwa-jiwa tegar untuk menerobos jalan buntu, merintis perdamaian Aceh.
Para perintis jalan itu sangat banyak, dikenal maupun tidak dikenal. Tulisan ini mencoba mengangkat satu fragmen saja. Lain tulisan dengan fragmen yang beda tentunya dengan orang-orang yang beda pula.
Pada satu kelok jalan damai yang hampir buntu, tersebutlah nama Tgk Nasruddin Bin Ahmed dan Tgk Ilyas Abed, serta Kolonel Ridwan Karim dam Naimah Hasan. Dua nama pertama dari Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) dan Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK) GAM. Dua nama lainnya dari KBMK dan KBAK RI.
Ketika perang di Aceh masih berkecamuk, dan perdamaian yang baru saja dirintis terancam gagal, pada 3 Agustus 2000, mereka berangkat ke Jenewa untuk mengikuti pertemuan bersama (joint forum) antara pimpinan GAM dan RI. Keempat mereka yang mengungkapkan kondisi nyata tentang perang Aceh dalam forum tersebut. Laporan mereka setidaknya menjadi semacam penegasan bahwa darah sudah banyak tumpah di Aceh dan saatnya untuk berdamai.
Mereka dengan difasilitasi Henry Dunat Centre (HDC) mampu meyakini para petinggi GAM dan RI untuk menghentikan dentuman senjata di Aceh untuk beberapa saat. Kepulangan mereka ke Aceh kemudian membawa rekomendasi bahwa harus dilakukan segera tindakan-tindakan yang terfokus dan praktis untuk membantu masyarakat sipil korban perang. Bantuan kemanusiaan harus tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.
Celah damai kembali terbuka, dan lubang untuk mengecor konstruksi perdamaian Aceh terus digali. Persoalan pengungsi harus disegerakan penyelesaiannya. Mereka harus dipulangkan ke rumah masing-masing dengan jaminan keamanan.
Namun damai belum juga wujud. Hujan peluru di kancah perang masih menembus raga Aceh. Tapi jiwa-jiwa Aceh yang sudah kandung basah bergelumut aroma darah, tak berhenti pada titik itu. Berbagai konsep dirancang dan dibahas untuk dibawa dalam forum bersama GAM dan RI. Bagaiman pun damai harus nyata di Aceh. Namun itu juga tidak mudah, kesepahaman bersama belum muncul. Akhirnya yang terjadi hanyalah debat konsep semata.
Ketaksepahaman itu juga menjalar ke tingkat tinggi di Swiss. Pada pertemuan forum bersama, 23 dan 24 September 2000. Masing-masing punya konsep yang itu tak mengantarkan mereka pada kesepahaman mendamaikan Aceh. Itikat sudah ada tapi setuju yang belum muncul.
Ada beberapa hal mendasar dalam konsep kedua pihak di KBMK itu yang berbeda, yakni: masalah penarikan TNI/Poltri non organik dari objek vital di Aceh. GAM menginginkan agar pasukan TNI/Polri yang ditempatkan di objek-objek vital segera ditarik ke tempat asalnya dan keamanan proyek tersebut diserahkan seluruhnya kepada satuan keamanan proyek-proyek tersebut. Hal ini ditolak oleh pemerintah RI.
Sementara masalah penarikan TNI/Polri dan GAM ke barak, GAM mengajukan konsep agar angkatan bersenjata RI dan GAM kembali ke barak masing-masing dan tidak dibenarkan keluar dari markasnya melebihi 500 meter, kecuali polisi dan bagi yang bertempat tinggal dalam lingkungan masyarakat sipil.
Begitu juga masalah membawa senjata api. GAM berpendapat TNI/Polri bisa membawa senjata api karena tugas yang telah disetujui oleh KBMK tetapi harus memakai uniform. Sebaliknya, pihak RI berpendapat TNI/Polri karena tugasnya dapat membawa senjata api dengan surat izin yang sah dari yang berwenang, dan bukan untuk melakukan serangan.
Sementara terkait masalah penghentian segala bentuk operasi, GAM menginginkan segala bentuk operasi dengan sandi apapun harus segera dihentikan karena dapat menimbulkan penderitaan rakyat. Tapi pemerintah RI terkait masalah ini menyatakan bahwa operasi kepolisian dengan sandi “cinta meunasah” dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan dasar yang telah disepakati dalam Komite Bersama Modalitas Keamanan.
Begitu juga dengan masalah penarikan TNI/Polri non-organik. Dalam konsep GAM, angkatan bersenjata RI non-organik harus segera ditarik dari Aceh, karena telah mengakibatkan pelanggaran Hak-hak Azasi Manusia (HAM) dan penderitaan rakyat Aceh. Pihak RI menolak hal tersebut.
Ketaksepahaman inilah yang membuat damai di Aceh tertunda. Meski jalan yang dirintis sudah menembus benua, tapi Aceh masih bergelut dalam darah. Ini yang harus kita pahami sekarang, bahwa langkah untuk mendamaikan Aceh itu bukanlah perkerjaan mudah.
Setiap rakyat Aceh harus memahami ini, bahwa menjaga perdamain merupakan kewajiban bersama. Meski menjaga dan merawat damai itu lebih susah dari membangunnya. Pada akhirnya kita kelak bisa berkata kepada anak cucu kita bahwa, ujeuén ka pirang, prang ka réuda. [Par]