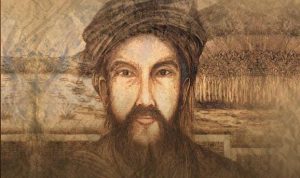Oleh: Isma Tantawi*
Abstract
The objective of this research is to analyze Didong Jalu in perspective of language aesthetic and social function on peoples of Gayo Lues ethnic group. The data in this research is analyzed based on both observation and documentation methods. The theoretical base used in this research is relied on literature sociological theoery suggested by Thomas Warton (1974) that literature work is considered to be expression of art and social document. Didong Jalu contains the language aesthetic value and it has social function for peoples of Gayo Lues ethnic group inhabiting the upland of Gayo Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia.
I. Pendahuluan
Didong sebagai tradisi lisan atau oral tradition (folklore) sudah berkembang sejak masuknya agama Islam di dataran tinggi Gayo, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia (L.K. Ara, 1995: 639). Agama Islam masuk ke Aceh pada abad ke-7 M. kira-kira 40 tahun setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat (Sutejo Sujitno, 1995: 71). Dalam Didong, sejak awal sampai saat ini nafas dan nuansa keislaman tetap bertahan. Bahkan Didong merupakan media dakwah untuk menyampaikan dan menyebarkan amanat keagamaan kepada masyarakat di samping menyampaikan pesan budaya suku Gayo itu sendiri.
Didong merupakan tradisi lisan suku Gayo sudah berakar dalam kehidupan masyarakatnya. Persembahan Didong diadakan pada pesta suka (pesta ayunan, pesta penyerahan anak kepada guru, pesta sunat rasul, dan pesta perkawinan) saja. Dalam Didong, diceritakan tentang kebudayaan suku Gayo, agama Islam (orang suku Gayo secara keseluruhan menganut agama Islam) dan masalah-masalah yang aktual, seperti peristiwa daerah, peristiwa nasional, dan peristiwa internasional.
Kata Didong, berasal dari bahasa Gayo, yaitu: dari akar kata dik dan dong. Dik, artinya menghentakkan kaki ke papan yang berbunyi dik-dik-dik. Kemudian dong, ertinya berhenti di tempat, tidak berpindah. Jadi, kata Didong dapat diartikan bergerak (menghentakkan kaki) di tempat untuk mengharapkan bunyi dik-dik-dik. Bunyi dik-dik-dik selalu digunakan untuk menyelingi persembahan Didong. Menurut kamus Bahasa Gayo – Indonesia, Didong ialah sejenis kesenian tradisional yang dipertandingkan antara dua Guru Didong yang berasal dari dua kampung yang berbeda. Persembahan dimulai setelah salat Isa sampai sebelum salat Subuh, (M.J. Melalatoa, 1985: 71).
Kata Didong menjadi nama kesenian tradisional di Gayo Lues berdasarkan cerita rakyat (foklore), yaitu: Asal-usul Gajah Putih yang dikumpulkan oleh Sulaiman Hanafiah (1984: 140 – 149). Gajah Putih merupakan penjelmaan dari seorang sahabat yang sudah meninggal dunia. Ketika Gajah Putih ini akan dibawa ke Istana Raja Aceh oleh orang-orang yang diperintahkan oleh raja. Gajah Putih tidak mau berjalan dan melawan. Gajah putih menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, sehingga menimbulkan bunyi dik-dik-dik. Namun demikian, ketika sahabatnya yang membawa, Gajah Putih pun berjalan dan sampailah ke Istana Raja Aceh.
Gerakan Gajah Putih yang menghentak-hentakkan kakinya ke tanah dan menimbulkan bunyi dik-dik-dik, selalu ditirukan oleh orang-orang yang melihat kejadian itu. Akhirnya kebiasaan tersebut dijadikan dan digunakan pada masa merasa gembira atau pada masa menyampaikan amanat dan nasihat kepada anak, teman, masyarakat atau kepada sesiapa saja yang dianggap perlu untuk disampaikan. Oleh sebab itu, kebiasaan tersebut berlangsung sampai saat ini dan disebut dengan tradisi lisan Didong Gayo.
Didong Gayo dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, Didong Gayo Lues. Didong Gayo Lues berkembang di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara. Didong Gayo Lues pada umumnya berbentuk prosa (bebas) dan hanya pada bagian tertentu saja yang disampaikan berbentuk puisi (terikat) seperti pantun. Isi cerita di dalam Didong Gayo Lues berhubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya.
Kedua, Didong Lut (Laut). Didong Lut berkembang di Kabupaten Aceh Tengah. Didong Lut berbentuk puisi (terikat). Isi Didong Lut tidak berhubungan secara langsung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Didong Lut seperti puisi yang dinyanyikan dan setiap puisi memiliki makna masing-masing.
Didong Gayo Lues dapat dibagi tiga macam; yaitu, Didong Alo (Didong penyambutan tamu), yaitu: Didong dipersembahkan untuk menyambut tamu. Pemain Didong Alo berjumlah lebih kurang 10 orang dari pihak tuan rumah dan 10 orang dari pihak tamu. Didong Alo dipersembahkan sambil berlari arah ke kiri atau ke kanan. Didong Alo berisi tentang ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih atas kehadiran tamu. Begitu juga dari pihak tamu mengucapkan terima kasih atas undangan dan sudah selamat diperjalanan sehingga dapat selamat sampai ke tempat tuan rumah.
Didong Jalu (Didong Laga), yaitu Didong dipersembahkan pada malam hari oleh dua orang Guru Didong yang diundang dari dua kampung yang berbeda. Setiap Guru Didong didampingi oleh pengiring yang berjumlah 10 sampai 20 orang. Pengiring berfungsi untuk mendukung persembahan. Pada bagian tertentu (adini Didong) cerita Didong disambut oleh pengiring sambil bertepuk tangan serta menggerakkan badan ke muka dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan.
Didong Niet (Didong Niat) selalunya dipersembahkan berdasarkan Niet seseorang. Misalnya Niet seseorang yang ingin mempunyai keturunan atau berkeinginan punya anak lelaki atau perempuan. Jika keinginan ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, maka Didong Niet ini pun dipersembahkan. Didong Niet ini mengkisahkan tentang anak yang diniatkan. Cerita dimulai dari awal pertemuan kedua orang tuanya. Kemudian pertemuan itu direstui serta dilanjutkan kepada jenjang peminangan dan pernikahan. Seterusnya cerita mengenai perkembangan bayi di dalam kandungan dan sampai bayi lahir ke dunia. Setelah itu cerita diteruskan ke pesta ayunan (turun mani) pemberian nama dihubungkan dengan hari kelahiran, agama (agama Islam), dan nama-nama keluarga seperti nama orang tua, kakek, nenek, dan lain-lain.
Cerita Didong yang menjadi objek penelitian ini adalah cerita Didong Jalu yang dipersembahkan oleh Guru Didong Ramli Penggalangan dan Idris Cike di Medan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2004. Persembahan dimulai pukul 21.45 dan berakhir pada pukul 04.30 WIB.
II. Didong Jalu Sebagai Karya Sastra (Tradisi Lisan)
Secara umum, karya seni dapat dibedakan menjadi lima bagian. Pertama, seni lukis, kedua seni suara, ketiga seni tari, keempat seni pahat (seni patung), dan kelima seni sastra. Kelima-lima seni tersebut di atas dibedakan oleh alat yang digunakan oleh pengarangnya. Seni lukis, alat digunakan oleh senimannya adalah garis dan warna. Seni suara, alat yang digunakan oleh vokalis dan istrumentalis adalah suara (vokal atau instrumental). Seni tari, alat yang digunakan oleh senimannya adalah gerak. Seni pahat atau patung, alat yang digunakan oleh senimannya adalah bentuk. Seni Sastra, alat yang digunakan oleh sastrawannya adalah bahasa (A. Teeuw, 1978 : 1).
Seni sastra yang lazim disebut sebagai karya sastra, menurut bentuk bahasa yang digunakan dapat pula dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, karya sastra disampaikan secara lisan dan kedua, karya sastra disampaikan secara tertulis atau bahasa tulis. Karya sastra lisan selalu disampaikan secara langsung kepada penonton atau penikmat. Karya sastra tulis disampaikan secara tertulis, seperti pada surat khabar, majalah, dan buku cetakan kepada pembaca atau penikmatnya.
Karya sastra lisan selalu dihubungkan dengan karya sastra lama, karena salah satu ciri-ciri sastra lama adalah cerita berbentuk lisan. Seterusnya ciri-ciri sastra lisan dapat ditunjukkan dari sudut yang lain. Sastra lisan merupakan milik masyarakat secara bersama dan tidak dikenal nama pengarangnya. Kini sastra lisan lebih dikenal dengan istilah tradisi lisan, (Mustafa Mohd. Isa, 1987: 1). Kemudian menurut Mohd. Taib Osman, ( 1976: 4), tradisi lisan oleh khalayak lebih dikenal lagi dengan istilah folklore.
Folklore berasal dari bahasa Inggeris yang terbentuk dari kata folk dan lore, (James Dananjaya, 1984 : 1-2). Folk ertinya kolektif dan lore ertinya tradisi dari sekelompok orang yang memilki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan yang dapat membedakan dari kelompok lainnya. Jadi, folklore adalah cerita rakyat (tradisi lisan) dari sekelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam bentuk bahasa lisan (Alan Dundes, 1965: 2).
James Dananjaya, (1984: 3-4), berpendapat ciri-ciri folklore adalah sebagai berikut:
i) Penyebaran dan pewarisannya selalu dilakukan secara liasan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut atau dengan contoh yang disertai dengan gerak dan alat bantu pengingat dari generasi ke generasi berikutnya.
ii) Folklore bersifat tradisional, yakni penyebarannya cukup lama atau minimal berlansung pada dua generasi.
iii) Dalam cerita folklore terdapat versi-versi dan variasi, yakni cerita yang bebeda menurut tempat dan waktu. Hal ini disebabkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), bukan melalui cetakan atau rekaman. Oleh sebab itu, proses lupa atau interpolasi (interpolation) dapat dengan mudah mengalami perubahan. Walaupun demikian, perbedaannya hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan.
iv) Foklore bersifat anonymous, yakni nama pengarang sebenarnya tidak dapat diketahui.
v) Foklore selalu mempunyai bentuk berumus atau berpola, yakni cerita tetap bertahan dengan pola yang sudah ada.
vi) Folklore mempunyai fungsi (function) pada masyarakat yang memilikinya secara kolektif.
vii) Folklore bersifat pralogik, yakni mempunyai sifak logik sendiri yang berbeda dengan logik yang berlaku secara umum.
viii) Folklore menjadi milik bersama (collective) dari kolektif tertentu. Hal ini disebabkan oleh penciptaan pertama tidak diketahui lagi. Oleh sebab itu, setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya.
ix) Folklore pada umumnya bersifat polos dan lugu. Oleh sebab itu, sering sekali terasa lemah, spontan, dan kasar. Ini dapat dimengerti karena folklore merupakan pengungkapan seni oleh manusia yang paling jujur.
Berdasarkan uraian di atas didapati bahwa Didong Jalu Gayo Lues dapat disebut sebagai karya sastra (tradisi lisan) karena Didong Jalu mengandung ciri-ciri tersebut. Pertama, Didong Jalu dipersembahkan secara liasan: yaitu, cerita didendangkan oleh kedua-dua Guru Didong secara bergantian. Pada bagian tertentu kedua-dua Guru Didong melakukan gerak-gerak tertentu pula. Misalnya pada bagian batang kedua-dua Guru Didong berjalan bolak-balik di atas papan persembaham. Pada bagian niro ijin kedua Guru Didong berdiri berhadapan dan melakukan gerak maju dan mundur.
Kedua, cerita Didong Jalu tumbuh dan berkembang sudah berlangsung lama di masyarakat Gayo Lues. Menurut sejarah Didong Jalu sudah berkembang di dataran tinggi Gayo Lues sejak masuknya ajaran Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Agama Islam masuk ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada abat ke 7 M. kira-kira 40 tahun setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat, (Sutejo Sujitno, 1995: 71).
Ketiga, cerita Didong memiliki versi-versi dan variasi. Versi Didong Jalu ada dua macam: yaitu, Didong Jalu Gayo Lues dan Didong Jalu Gayo Lut. Kedua-dua Didong ini bersisi tentang mengadu ketangkasan antara satu Guru Didong dengan Guru Didong lainnya. Namun demikian, cara dan pola persembahannya berbeda. Pola persembahan Didong Jalu dimulai dengan permulaan persembahan (Didong Tuyuh), persalaman (tabini Didong), kesepakatan (batang), berteka-teki (itik-itiken), dan mohon maaf (niro ijin) sedangkan Didong Jalu Gayo Lut berpola persalaman, isi, dan penutup.
Kempat, pencipta Didong Jalu yang sebenarnya tidak dapat diketahui, karena Didong Jalu dituturkan secara lisan oleh Guru Didong terdahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui bahasa lisan. Oleh sebab itu, Didong Jalu menjadi milik bersama masyarakat Gayo Lues. Didong Jalu yang digunakan untuk objek kajian ini merupakan seni ulang yang yang dilakukan oleh kedua-dua Guru Didong; yaitu, Ramli Penggalangan dan Idris Cike. Namun seni ulang pun tetap memiliki nilai seni tersendiri yang berbeda dengan seni cipta yang pertama, (Sidi Gazalba, 1974: 425).
Kelima, cerita Didong Jalu didendangkan oleh kedua-dua Guru Didong melalui pola yang sama. Pola Didong Jalu itu dimulai dengan permulaan persembahan (Didong tuyuh). Pada bagian ini kedua-dua Guru Didong masih dalam keadaan duduk. Cerita masih berisi tentang pengantar atau memperkenalkan Guru Didong yang akan tampil dalam persembahan. Pada bagian persalaman (tabini Didong) kedua-dua Guru Didong berdiri berdampingan dan cerita berisi tentang persalaman kepada para penonton persembahan. Pada bagian kesepakatan (batang) kedua-dua Guru Didong berjalan secara bolak-balik di atas papan persembahan. Cerita di sini berisi tentang kesepakatan kedua-dua Guru Didong tentang persembahan Didong Jalu pada bagian berikutnya. Pada bagian berteka-teki (itik-itiken) kedua-dua Guru Didong pada keadaan berdiri berdampingan dan cerita berisi tentang teka-teki yang sudah disepakati pada bagian batang. Kemudian cerita Didong Jalu ditutup dengan bagian mohon maaf (niro ijin). Kedua-dua Guru Didong berdiri berhadapan sambil bergerak maju dan mundur dan cerita berisi tentang permohonan maaf antara kedua-dua Guru Didong dan kepada para penonton persembahan.
Keenam, cerita Didong Jalu berguna bagi masyarakat Gayo Lues. Secara khas Didong Jalu digunakan pada pesta suka saja. Pesta suka dalam masyarakat Gayo Lues ada empat macam: yaitu, pertama pesta ayunan, kedua pesta penyerahan anak kepada guru, ketiga pesta sunat rasul, dan keempat pesta perkawinan.
Ketujuh, dalam cerita Didong Jalu terdapat logika yang berbeda dengan logika yang belaku secara umum, seperti contoh berikut ini:
i) Ramli Penggalangan dan Idris Cike yang berprofesi sebagai Guru Didong. Kedua-dua Guru Didong masih menganggap persembahan Didong Jalu sebagai pekerjaan yang memalukan untuk orang yang berumur atau sudah punya anak gadis atau lajang. Ramli Penggalangan berumur 43 tahun dan Idris Cike berumur 40 tahun pada waktu persembahan Didong Jalu ini dilakukan. Seperti diceritakan oleh Guru Didong berikut ini:
“Pada malam yang berbahagia ini, sudah jelas bergelinding telur di tanah yang rata. Memecahkan empedu di ujung kaki, memekakkan telinga membutakan mata. Kita bercerita di atas papan persembahan ini.” (Ramli Penggalangan, paragraf: 40).
ii) Guru Didong selalu menganggap dirinya orang yang tidak mengetahui dan tidak berpengalaman apa-apa tentang cerita Didong Jalu, adat, dan agama walaupun kedua-dua Guru Didong yang sudah berpengalaman tentang Didong Jalu dan menguasai masalah agama dan adat. Seperti diceritakan Guru Didong Idris Cike, (paragraf: 07) berikut ini:
“Yang kami punya ini pun tidak berpengalaman. Seperti kerbau masuk kampung yang serba kebingungan. Badannya cuma besar, umurnya masih muda. Seperti kayu kering, sangat cepat dilalap api. Jika digertak mudah takut, kalau ditakuti mudah terkejut. Begitu pula kalau bercerita lebih banyak yang lupa dari yang diingat. Seperti anak masih belum pandai dan masih memerlukan pelajaran dan pendidikan. Cerita dan jalan cerita pedas seperti cabai merah, pahit seperti rimbang hutan.”
iii) Pada saat Guru Didong A menanyakan pertanyaan teka-teki kepada Guru Didong B atau sebaliknya, Guru Didong tidak boleh menjawab secara langsung, tetapi harus diselidiki dengan pertanyaan yang lain dan behubungan dengan pertanyaan teka-teki yang sedang ditanyakan.
Kedelapan, cerita Didong Jalu merupakan milik bersama masyarakat Gayo Lues. Sudah menjadi sifat tradisi lisan, di samping nama pengarang tidak dapat diketahui, dalam tradisi lisan selalu diceritakan tentang adat dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi lisan menjadi milik masyarakat di mana tradisi lisan itu diciptakan. Isi cerita tradisi lisan itu menggambarkan kehidupan masyarakat yang bersangkutan, (Mohd. Taib Osman, 1976: 7).
Kesembilan, isi cerita Didong Jalu berisi polos dan lugu karena pada umumnya penutur tradisi lisan adalah orang-orang berbakat alami dan tanpa memperoleh pendidikan yang resmi. Oleh sebab itu, apa saja yang diceritakan adalah pengungkapan yang sebenarnya dan tanpa rekayasa. Didong Jalu adalah penngungkapan pemikiran kedua-dua Guru Didong. Sejalan dengan pendapat Rene Wellek (1995, 111) bahwa seniman menyampaikan kejujuran dan kebenaran sejarah dan peristiwa sosial yang berlaku.
III. Didong Sebagai Dokumen Sosial Masyarakat Gayo Lues
Karya sastra dibangun dari dua unsur; yaitu, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun karya sastra dari bagian dalam seperti alur, tokoh, gaya bahasa, tema, dan suasana. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar seperti agama, adat, psikologi, kesehatan, dan hukum. Dunia sastra adalah dunia yang sangat luas, dalam karya sastra terpancar semua kehidupan manusia.
Setiap suku bangsa memiliki pengungkapan seni. Pengungkapan seni setiap suku bangsa selalu berberda. Perbedaan ini timbul karena setiap suku bangsa memiliki cara hidup yang berbeda pula. Perbedaan cara hidup ini menimbulkan perbedaan seni yang dilahirkan setiap suku bangsa. Misalnya, suku Jawa, terkenal dengan tradisi lisan Wayang, suku Batak, terkenal dengan tari Tor-tornya, suku Melayu, terkenal dengan tari Serampang Dua Belas dan suku Gayo Lues terkenal dengan tradisi lisan Didongnya.
Setiap seni yang dilahirkan suku bangsa selalu mengambarkan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena seniman merekam semua peristiwa kehidupan di dalam karya seni yang diciptakan. Lahirnya sastra adalah merupakan keinginan yang mendasar dari manusia untuk mengungkapkan diri, untuk menaruh minat sesama manusia, untuk menaruh minat pada dunia realitas dalam angan-angan yang dikhayalkan sebagai dunia nyata, (Andre Harjana, 1981: 10).
Sapardi Joko Damono, (1978: 1) berkata, sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya dan bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Sastra adalah produk suatu masyarakat dan mencerminkan masyarakatnya. Pemikiran masyarakatnya merupakan pemikiran pengarangnya, (Jakob Sumarjo, 1979: 30).
Rene Wellek, (1995: 111) berpendapat, pengarang menyampaikan kebenaran pada waktu yang sama juga merupakan kebenaran sejarah dan sosial. Karya sastra merupakan dokumen sosial. Oleh sebab itu, apa yang tergambar di dalam karya sastra merupakan kenyataan-kenyataan yang ada atau sudah pernah ada di dalam kehidupan sosial.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, bahwa karya sastra bukan lahir begitu saja, tetapi akibat pengaruh hubungan antara pengarang dengan masyarakatnya. Pengarang menciptakan karya sastra bukan berdasarkan khayalan belaka, tetapi khayalan yang terinspirasi dari kenyataan dan fakta yang ada di dalam masyarakat. Pengarang dan pemikiran masyarakat sangat memegang peranan penting di dalam karya sastra, karena sastra dibangun dari pemikiran masyarakatnya.
Tradisi Lisan Didong Jalu lahir dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Gayo Lues. Didong Jalu mengandung pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan masyarakat Gayo Lues. Pemikiran berupa adat, budaya, dan agama yang sudah atau sedang dilakukan oleh masyarakat Gayo Lues. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Didong Jalu merupakan dokumen sosial bagi masyarakat Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia.
IV. Keindahan Bahasa Dalam Didong Jalu
Karya sastra berbeda dengan karya ilmiah. Karya sastra mengandung nilai seni sedangkan karya ilmiah tidak. Perbedaan ini timbul karena karya sastra disampaikan pengarang dengan ragam bahasa sastra yang berbeda dengan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa sastra sangat bergantung kepada sastrawan atau seniman sedangkan ragam bahasa ilmiah harus mengikut kepada pedoman tata bahasa dan makna yang sudah ada, (V.I. Braginsky, 1984: 7).
Ragam bahasa dalam karya sastra, di samping pemilihan kata, sastrawan juga menggunakan gaya bahasa seperti hiperbola, personifikasi, inversi, pleonasme dan lain-lain. Sastrawan menggunakan gaya bahasa ini bertujuan untuk mempertegas atau untuk lebih menghidupkan suasana di dalam cerita. Dengan pemilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan para sastrawan atau seniman, karya sastra lebih diminati dan disenangi oleh pembaca atau penonton, karena di samping keindahan alam, karya sastra mengandung nilai keindahan seni, (Wajiz Anwar, 1980: 5).
A. Richard, C.K. Ogden dan James Wood ,(lihat Sohaimi Abddul Aziz, 2000: 2), berpendapat, salah satu dasar keindahan adalah medium. Medium sastra adalah bahasa. Didong Jalu sebagai salah satu karya sastra yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Seperti cerita Guru Didong Ramli Penggalangan (paragraf: 02) berikut ini:
“Tak ada laba-laba yang menutupi tangga, tak ada buaya yang menghadang di jalanan. Kami sudah hadir memenuhi undangan, yang disampaikan melalui selembar sirih, sekeping gambir, segores kapu,r dan sepotong pinang.”
Kejayaan mengeksploit medium bahasa dengan baik, dapat menghasilkan kepuasan psikologi kepada para pembaca atau penonton persembahan. Kepuasan psikologi yang dapat diperoleh dari karya sastra yang berhubungan dengan kesempurnaan, kehalusan, kematangan, dan kepekaan yang dapat memberikan kesan makna dan emosi, (Sohaimi Abdul Azizz, 2000: 8).
Kesan makna dan emosi yang berhubungann dengan peristiwa aktual yang diceritakan Guru Didong seperti berikut ini:
“Ayah dan ibuku, berlari-lari menyelamatkan nyawa. Di daerah Aceh sudah terjadi, rakyat mengungsi semakin susah. Orang yang melakukannya yang tidak jelas, yang korban rakyat biasa. Entah apa sebabnya, tiba-tiba terjadi kontak senjata.” (Idris Cike, paragraf: 54).
Bahasa yang digunakan Guru Didong dengan amat baik dapat menimbulkan bunyi dan irama pada kata-kata yang terpilih dan disusun. Oleh sebab itu, dapat menimbulkan kesan yang makna mendalam kepada para pembaca atau penonton. Seperti cerita Didong Jalu yang disampikan dalam bentuk pantun berikut ini:
“Hijau-hijau gununglah hijau,
Siamang memanggil setengah hari.
Sia-sia badanmu muda,
Jika tidak berani mati.
Burung balam gunung bersuara merdu,
Akan kupetik dengan ujung jari.
Bulu keliling warna yang menarik,
Supaya jinak, saya petik lagi.” (Idris Cike, paragraf: 65).
Menurut Agus Sachari, (1989: 1), keindahan sebenarnya merupakan hal yang utama di dalam kehidupan kita, karena tanpa keindahan, hidup ini terasa merana dan kehilangan kebahagiaan. Semua pencipta karya sastra yang baik, adalah manusia perasa yang bukan sedikit melibatkan pemikiran dan perasaan dalam peroses mengarang itu. Pilihan kata dan irama yang ada di dalam karya sastra merupakan alat untuk menyampaikan fikiran dan perasaannya kepada para pembaca atau penonton, (Muhammad Haji Saleh, 1992: 14).
Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tradisi Didong Jalu yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, terasa sangat indah dan menarik bagi penontonnya. Indah dan menarik ini terjadi karena pilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh kedua-dua Guru Didong di dalam Didong Jalu. Oleh sebab itu, para penonton persembahan dapat bertahan menonton persembahan, sampai menjelang salat Subuh serta dapat menangkap makna yang tersurat dan tersirat di dalam Didong Jalu.
V. Fungsi Sosial Didong Jalu
Didong Jalu yang lahir dan berkembang pada kehidupan masyarakat Gayo Lues, karena Didong Jalu memiliki fungsi sosial tertentu bagi masyarakat Gayo Lues. Oleh sebab itu, Didong Jalu tidak pernah terlepas dari suku Gayo Lues. Dalam Didong Jalu tergambar pemikiran-pemikiran dan budaya suku Gayo Lues secara menyeluruh. Didong Jalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gayo Lues yang dilakukan dan berkembang sampai kini.
Menurut Alan Dundes, (1965: 277), fungsi sosial tradisi lisan atau folklore itu ada 5 macam; yaitu, i) membantu pendidikan, ii) meningkatkan perasaan solidaritas kelompok, iii) memberi sanksi sosial agar orang berprilaku baik, iv) sebagai alat kritik sosial, dan v) sebagai hiburan.
Berdasarkan pendapat di atas, maka Didong Jalu dapat dilihat fungsi sosialnya bagi masyarakat Gayo Lues seperti berikut ini:
i) Dalam Didong Jalu, Guru Didong menyampaikan pendidikan secara langsung mahupun tidak langsung kepada penonton persembahan. Pendidikan langsung; yaitu, Guru Didong langsung memberikan penjelasan kepada penonton persembahan. Misalnya Guru Didong Ramli Penggalangan (paragraf: 24-27) menjelaskan tentang makna ralik, juelen, sebet, dan guru dalam masyarakat Gayo Lues. Ralik pihak keluarga dari isteri yang harus dilayani oleh pihak keluarga suami, karena ralik adalah status yang paling mulia di dalam masyarakat Gayo Lues. Juelen, pihak keluarga menantu laki-laki bertugas untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang berat dalam pesta. Pihak menantu laki-laki ini bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan pesta. Sebet adalah orang-orang yang dikenal karena pergaulan hidup sehar-hari dan terjadi hubungan yang baik. Oleh sebab itu, selalu menjadi teman suka dan duka di dalam kehidupan sehar-hari. Guru adalah orang yang mengajari dan memberikan petunjuk semoga selamat di dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan tidak langsung dapat pula dilihat pada keseluruhan persembahan Didong Jalu. Persembahan Didong Jalu dimulai dari awal sampai akhir mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Oleh sebab itu, Guru Didong secara tidak langsung telah memberikan penjelasan kepada penonton persembahan bahwa persembahan Didong Jalu harus berlaku seperti yang ia lakukan.
ii) Jika dilihat dari cara pelaksanaan persembahan dan isi cerita, ternyata Didong Jalu dapat meningkatkan perasaan solidaritas kelompok. Pada masa pelaksanaan persembahan Didong Jalu, diundang semua ahli famili dari semua kampung dan semua ahli famili itu membawa semua kenalan, sahabat, dan tetangga yang ada di kampung ahli famili yang diundang. Dengan demikian, setiap diadakan persembahan Didong Jalu akan terjadi pertemuan masyarakat antara satu kampung dengan kampung lain. Pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang ini akan dapat meningkatkan perasaan solidaritas kelompok bagi masyarakat Gayo Lues.
Begitu juga dari isi cerita Didong Jalu, ia dapat meningkatkan perasaan solidaritas kelompok antara Guru Didong dengan Guru Didong dan antara masyarakat dengan masyarakat penonton persembahan. Meningkatkan perasaan solidaritas antara Guru Didong dengan Guru Didong seperti dikemukakan Guru Didong Idris Cike (paragraf: 65) bahwa cerita Didong Jalu ini bertujuan untuk menjadi lebih kenal seperti menjadi satu ayah satu ibu. Didong Jalu juga dapat meningkatkan perasaan solidaritas antara masyarakat dengan masyarakat Gayo Lues.
iii) Isi cerita Didong Jalu dapat memberikan sanksi sosial kepada masyarakat agar masyarakat dapat berbuat baik. Seperti diceritakan Guru Didong Ramli Penggalangan (paragraf: 21) berikut ini:
“Jika ada yang berlaku, yang kotor salah sentuh, yang pantang salah ucap. Semua dosa dan pahalanya menjadi tanggungannya dan panitia bebas dari dakwaan. Uang tidak tertentu jumlah rupiahnya, ditahan tidak tertentu jumlah tahunnya. Mahkamah dan meja hijau yang berkuasa untuk memutuskan hukumannya.”
iv) Didong Jalu juga dapat dijadikan alat kritik sosial bagi masyarakat Gayo Lues. Di dalam Didong Jalu Guru Didong memberikan keritikan-kritikan sosial kepada masyarakat Gayo Lues. Seperti diceritakan Guru Didong Idris Cike (paragraf: 53) berikut ini
“Ilmu hanya diketahui oleh orangtua, pedoman pun sudah hilang di tengah hutan belantara. Oleh sebab itu, saya bercerita hanya sedikit yang ingat dan lebih banyak yang lupa, begitu pun tetap kutabahkan hatiku. Pada malam ini, hanya ilmu kita yang akan kita sampaikan, fikiran kita yang akan kita jelaskan. Harap didengarkan dan difikirkan bapak, ibu, dan saudaraku, supaya ada manfaat menonton persembahan ini.”
v) Didong Jalu dapat menjadi hiburan bagi masyarakat Gayo Lues. Biasanya terdapat dua hal yang ingin disampaikan oleh pengarang karya sastra. Pertama, pengarang ingin menyampaikan amanat yang berupa pemikiran-pemikiran. Kedua, karya sastra untuk menghibur para penikmat atau penontonnya. Oleh sebab itu, di samping untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran Didong Jalu ternyata menjadi hiburan bagi masyarakat Gayo Lues seperti diceritakan Guru Didong Ramli Penggalangan (paragraf: 44) seperti berikut ini:
“Sudah ada kesempatan dan sudah ada kelapangan. Sunyi untuk diramaikan, ramai untuk dimeriahkan. Supaya jangan menjadi penghambat kemajuan untuk mencapai masa hadapan yang cerah, diundang keluarga bapak, dikumpulkan keluarga ibu diadakan persembahan Didong Jalu untuk hiburan.”
VII. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian terhadap Didong Jalu di atas, penulis menyusun dapatan sebagai berikut: Pertama, Didong Jalu mengandung nilai keindahan bahasa, karena kemampuan Guru Didong menggunakan pilihan kata yang baik serta pemkaian irama yang sesuai. Kedua, Didong Jalu memiliki fungsi sosial bagi masyarakat Gayo Lues, yaitu: untuk menyampaikan pendidikan, untuk meningkatkan solidaritas, memberikan nasihat, sebagai alat untuk menyampaikan kritikan sosial, dan untuk hiburan bagi masyarakat Gayo Lues. Oleh sebab, itu Didong Jalu dapat dianggap sebagai dokumen sosial bagi masyarakat Gayo Lues.
Sebagai kesimpulan untuk keseluruhan penelitian ini, bahwa Didong Jalu sebagai karya sastra atau taridisi lisan merupakan milik masyarakat Gayo Lues dan mengambarkan kehidupan masyarakat Gayo Lues itu sendiri. Didong Jalu memiliki keindahan bahasa dan fungsi sosial bagi masyarakat Gayo Lues. Didong Jalu perlu dilestarikan, sehingga dapat berkembang dengan baik dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
Daftar Bacaan
Agus Sachari. 1989. Estetika Terapan. Bandung: Nova.
Andre Harjana. 1981. Kritik Sastra Sebuah Pengantar. Jakarta: PT Gramedia.
Braginsky, V.I. 1994. Erti Keindahan dan Keindahan Erti Dalam Kesusastraan Melayu Klasik (Terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Dundes, Alan. 1965. The Study of Folklore. America: Prentice-Hall, Inc.Englewood Cliff, N.J.
Jakob Sumarjo. 1979. Masyarakat dan Sastra Indonesia. Yogyakarta: CV Nur Cahaya.
James Dananjaya. 1984. Folklore Indonesia. Jakarta: Grafitipers.
L.K. Ara. 1995. Seulaewah, “Antologi Sastra Aceh Sekilas Pintas”.Jakarta:Yayasan Nusantara.
M. Junus Melalatoa. 1985. Kamus Bahasa Gayo Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Muhammad Haji Saleh. 1992. Puitika sastra Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd. Taib Osman. 1976. Panduan Pengumpulan Tradisi Lisan Malaysia. Malaysia: Malindo Printers Sdn. Bhd.
Mustapa Mohd. Isa. 1987. Awang Belanga PelipurLara dari Perlis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Sidi Gazalba. 1974. Sitematika Falsafah. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Berhad.
Sohaimi Abdul Aziz. 2000. “Estetika Kesusastraan Melayu: Satu Pandangan Muhammad Haji Saleh”. Pulau Pinang: Seminar Kefahaman Budaya Ke IV.
Sulaiman Hanafiah. 1984. Sastra Lisan Gayo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Sutejo Sujitno, 1995. Aceh Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan. Banda Aceh: Sekretariat Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
Teeuw, A. 1978. “Penelitian Struktur Sastra”. Tugu Bogor. Kertas Kerja.
Wadjiz Anwar, 1980. Falsafah Estetika. Yogyakarta: Nur Cahaya.
Warton, Thomas. 1974. History of English Poetry. London: The Universiti of Chicago Press.
Wellek, Rene, 1995. Teori Kesusastraan (Terjemahan). Jakarta: PT Gramedia.
Isma Tantawi
Isma Tantawi lahir pada tanggal 7 Februari 1960 di Kuning Aceh Tenggara (sekarang Kabupaten Gayo Lues). Beliau adalah staf pengajar tetap di Fakultas sastra Universitas Sumatera Utara mengasuh mata kuliah Sastra Bandingan, Estetika, dan Sastra Malaysia Modern serta mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara dan sebagai dosen tamu di Kolej Sentral Kuala Limpur, Malaysia. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara tahun 1986 dan saat ini sedang mengikuti pendidikan master (S-2) di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia dengan bidang kajian tradisi lisan nusantara. Di samping itu juga beliau aktif mengikuti seminar nasional dan internasional baik sebagai peserta maupun pemakalah. (ismatantawi.blogspot.com)
*Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara