Oleh : Novarizqa Saifoeddin
Mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat agresi militer kedua Desember 1948.
Belanda bergerak memperluas serangan dari Medan- Langkat – Tanah Karo lalu dikabarkan akan menuju Aceh.

Tahun 1949, usiaku 23 tahun kala itu. Di Negara tercinta ini, banyak terdapat Negara-negara boneka bikinan Belanda. Satu di antaranya Negara Sumatera Timur (NST) di Medan. Ini berarti Belanda dan kaki tangannya yang dikenal dengan NICA, berada di Medan serta dimungkinkan untuk menuju ke Aceh.
Dengan semangat menyala menggelora demi mempertahankan kemerdekaan, pasukan kami dari Gayo, dengan baju seragam hitam, celana hitam, ada yang bersepatu ada yang tidak, ada anak muda, ada yang sudah tua, berangkat ke front Tanah Karo . Tanah Karo, adalah satu diantara banyak front perang di serata tanah air waktu itu. Tiba disana, pasukan kami lalu bergabung dengan gerilyawan Tanah Karo yang dikomandani Selamat Ginting.
Sugihan, sebuah desa di Tanah Karo menjadi tempat tinggal kami. Lebih kurang setelah 15 hari disana, aku diperintahkan pimpinan kembali ke Takengon. Secepat mungkin walaupun dalam bulan ramadhan. Pulang untuk menghubungi tokoh-tokoh yang bisa mengurus perbekalan perang kemudian mengirimkan ke front dengan segera.
Dengan sehelai baju yang lekat dibadan, celana panjang warna hitam, sepatu ATC serta kain sarung mengikat melilit di pinggang, aku berpisah dengan pasukan. Kepadaku ditawarkan pistol tapi aku tak menerimanya. Menemaniku, sebilah pisau sepanjang sehasta, tanda mata dari Ama Pengulu Gayo dari desa Kutelintang, tergantung di pinggangku. Sepucuk Surat Keterangan yang sewaktu waktu bisa membantuku diperjalanan.
Beberapa hari jalan kaki sendirian, dari Sugihan melewati ladang, desa pemukiman gerilyawan dan penduduk yang mengungsi, akupun tiba di Kutacane. Hari itu 27 ramadhan. Aku beristirahat dirumah seorang penduduk. Badan ini serasa hancur luluh. Perjalanan masih sangat jauh untuk sampai ke Gayo, melewati Belangkejeren, Owak dan jika beruntung dari Owak bisa naik oto ke Takengon.
Sambil beristirahat itu aku berpikir, aku akan berlebaran dimana. Berjalan sendirian dari Kutacane ke Belangkejeren melewati hutan rimba belantara, terlalu naif. Kuusahakan mencari teman, yakni pedagang pedagang yang berkuda beban tapi mereka sudah lebih dulu pergi.
Dengan penuh keihlasan dan semangat menjalankan tugas membela tanah air, pagi pagi benar, 29 ramadhan, aku angkat langkah. Mulia Karo-Karo, si empunya rumah tempatku menumpang memberiku lima lembar uang kertas seringgit dan sebambu beras sebagai bekal diperjalanan.
Hari agak mendung, hingga aku melewati Macan Kumbang, aku belum bertemu seorangpun yang bisa menjadi teman dalam perjalanan menuju Belangkejeren. Hatiku keras, tekadku kuat. Sedapat mungkin aku harus selamat sampai di Belangkejeren dan berlebaran disana.
Jarak beberapa ratus meter didepanku, ada sesosok tubuh. Tidak jelas, Di hutan lebat itu gerimis dan berkabut. Entah manusia entah harimau. Orang menyebut tempat ini Gunung Setan. Hatiku berdebar-debar. Akan mundur atau terus maju. Mundur kemana, tak tau juga tapi mau terus maju juga penuh resiko. Bagaimana kalau sosok itu harimau..?
Langkahku kuteruskan. Sosok itu kian jelas. Manusia berpayung kain hitam. Menggendong bekalnya dengan kain sarung. Makin lama makin dekat. Ia ternyata memperlambat langkahnya dengan harap bertemu seseorang sebagai teman. Debar jantungku telah berakhir, kami kini berteman sudah.
Sepanjang perjalanan kami lebih banyak diam. Hanya ada keesaan tujuan yakni agar akhir ramadhan kami sudah memasuki Belangkejeren. Kami sepakat berjalan lebih cepat. Sekitar jam Sembilan malam, kami tiba di Gumpang dan menumpang di pondok seorang Bibik Jawa. Sambil menanti bibik mempersiapkan makanan, kami dipersilahkan beristirahat.
Setelah nasi dipiring masing-masing, temanku mengeluarkan rantang dari kain sarung, isinya rendang daging, telah hitam. Mengertilah aku kalau temanku ini jelas orang Padang. Ia rupanya harus segera tiba di Belangkejeren karena istrinya sakit disana. Sedang aku harus segera pulang ke Takengon untuk urusan perang dan mengejar Belangkejeren adalah ingin shalat id di sana.
Pagi benar, setelah menikmati kopi dan ketan yang dipersiapkan Bibik Jawa, kamipun berpamitan dengan baik. Dan melanjutkan perjalanan.
Di Palok hari sudah gelap. Tempat ini padang ilalang, kawasan harimau. Berbelas kilometer lagi jarak yang harus ditempuh. Menginap tidak mungkin. Kami satu bahasa, jalan terus..!
Setelah menyeberangi sungai Wih Ni Penampakan, kamipun tiba di Belangkejeren. Temanku yang orang padang dari Bayur itu mengajakku bermalam dirumahnya tapi aku menolak mengingat ia sedang dalam suatu urusan. Istrinya sakit keras.
Aku menginap di rumah pak Mantri Hewan Hasan. Kedatanganku disambut dengan pertanyaan, Kenapa pulang, Apakah ada yang luar biasa penting, Bagaimana keadaan pasukan kita dan sebagainya.
Setelah kujelaskan sekedarnya sambil menikmati makan dan kopi, aku dipersilahkan untuk tidur.Maryam Hasan, gadis penghuni rumah itu, menyiapkan sebuah rusbang di jalan turun tangga menuju dapur.
Badanku sangat letih, walau barusan aku telah mandi. Berhari-hari berkeringat, dengan baju hanya sehelai, rambut dan jenggot tak berurus. Betapapun kutidurkan badan ini, kupejamkan mataku, aku tetap tak bisa tidur. Terbayang terkenang berbagai hal. Teringat kawan kawan di front, tugas yang dibebankan kepadaku harus selesai seceptnya, mengingat dari Takengon nanti aku masih harus keLangsa dan ke Kutaraja. Teringat ibu dan bapak di kampung berhari raya tanpa aku. Dua anaknya pergi perang. Bermacam macam, tapi yang segera harus kupecahkan ialah, bagaimana aku besok berhari raya. Mungkinkah dengan baju hitam, celana hitam dan sarung yang bau tidak bercuci..? Sebuah pertanyaan yang membuatku tak bisa tidur.
Sebentar kemudian pak Hasan memanggilku. Hari telah larut malam. Di depan istrinya Inen Riyem, di depan putrinya Maryam Hasan, aku duduk berhadapan. Di depan pak Hasan sesumpit kecil beras ukuran fitrah seorang jiwa.
“Tengku” kata pak Hasan. “ Tengku musafir, sabilullah. Ini hak tengku. Fitrahku untuk tengku, agar diterima”. Ia mengulurkan tangannya untuk kujabat. Berat hatiku menerimanya, tapi tanganku ditarik dan kami berjabatan. Ini berarti fitrahnya telah kuterima. Air mataku bercucur kepipi yang bereokan. Kata terima kasih tak sanggup kuucapkan, hanya tangis tanpa suara sambil beranjak menuju rusbang, beberapa saat kemudian akupun tertidur.
Beduk subuh bertalu talu pertanda 1 syawal telah datang. Orang-orang ramai turun dari rumah untuk pergi berlangir ke pemandian. Maryam Hasan membangunkanku. Kepadaku diberikannya sebuah timba, didalamnya sehelai baju kemeja bersih, sehelai kain sarung, sisir, sabun mandi, limau purut. Di pagi berkabut itu, aku jalan ke Wih Ni Penampakan, sebuah sungai yang jernih airnya.
Tiba di air itu, aku tidak segera mandi, limau purut yang telah diiris-iris itu kuremas-remas. Kakiku separuh dalam air, mataku kuyup terus. Alangkah baiknya keluarga pak Hasan. Dibuatnya diriku seakan harus merasakan bahwa aku berada di dekat ibu kandungku berhari raya bersama. Selesai mandi, kupakaikan sarung dan kemeja tadi, tangisku makin menjadi. Baju dan celana hitam serta sarungku sempat juga ku cuci.
Tiba di rumah, Maryam Hasan menyuguhkan minuman dan kue. “enti uwes tu ate, bang” tuturnya. Jangan terlalu bersedih, bang. “Kita kan sedang berjuang” lanjutnya. Tersentak terhenti tangisku, malu aku padanya. Perang dan idul fitri ini, sungguh mengharukan.
Usai shalat Id dilapangan, aku diajak berlebaran, menjadi tamu dari satu rumah ke rumah lain, menikmati suasana yang bertempur berkecamuk dalam sanubari.
Pada tiga hari raya, kuteruskan perjalanan. Dari Belangkejeren jalan kaki menuju Owak. Perjalanan ini tidak sesulit sebelumnya. Aku bertemu teman orang Karo bernama RN Maha dan pak Munap yang hendak mengantar anak gadisnya Rusminah yang akan masuk sekolah usai liburan di Sekolah Guru.
Dari Owak kami menaiki oto milik Sepir Salam. Oto tak berlampu. Jalan malam di Bur Lintang yang serem itu hanya dengan bayangan bulan dan obor damar. Kondekturnya jalan kaki di depan dengan obor, otonya mengikuti pelan-pelan. Alhamdulillah kami selamat tiba di Takengon.
Melewati Gumpang dan Gunung Setan. Melewati hari raya yang haru biru, berarti melewati juga saham saham perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia oleh berbagai oknum. Kepada Allah Yang Rahman dan Rahim, kumintakan ganjaran terhadap mereka.
Begitulah sekelumit cerita seorang pejuang BAGURA dari Tanoh Gayo, Aceh Tengah tentang perang dan Idul Fitri yang dituturkan padaku. Aman Ona, begitulah orang-orang di kampung menyapanya. Usianya kini delapan puluh enam tahun, bermukim di Kota Depok- Jawa Barat. Insya Allah ia hidup bahagia bersama istri, dengan lima orang anak dan 15 cucu.
Cerita perang mempertahankan Indonesia, melibatkan oknum berbagai etnis, Karo, Jawa, Padang, Gayo, mempertunjukkan kegotong royongan, ramah dan kemurahan hati.
Bukankah ini sangat Indonesia….?
(Tulisan ini diikutsertakan dalam Kompetisi Blog Paling Indonesia yang diselenggarakan oleh Telkomsel bekerjasama dengan Kompasiana-http://sejarah.kompasiana.com/2011/04/28/perang-dan-idul-fitri/)






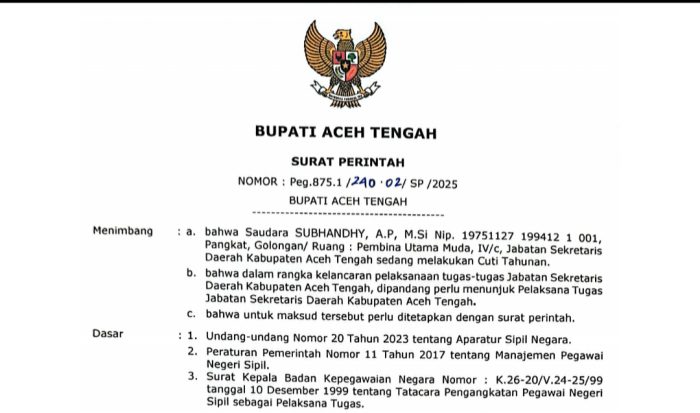



Berjalan kaki dari Sugihan hingga Owak, melewati hutan belantara dengan ancaman binatang buas demi mempertahankan kemerdekaan. Meninggalkan kedua Orang tua, berlebaran di rumah orang, sungguh kisah yang mengharu biru.
Bersyukur kita kedua kakak beradik ini selamat dan menjadi saksi sejarah.
Terima kasih LoveGayo.
setelah baca ini saya seolah membayangkan bagaimana akses dari tanah karo pada era penjajahan belanda waktu itu. Tragis kalau saat ini setelah merdeka justru banyak Pejabat yang bermental BIADAB dan berubah jadi pencuri dengan gaya yang exklusive,mereka bahakan tak pernah tau betapa ikhlasnya Pejuang ini demi kehidupan kita saat ini, semoga kebahagian tetap menyertai Awan awan nteni amin…Amin…Amin… Berijin Awan…:-