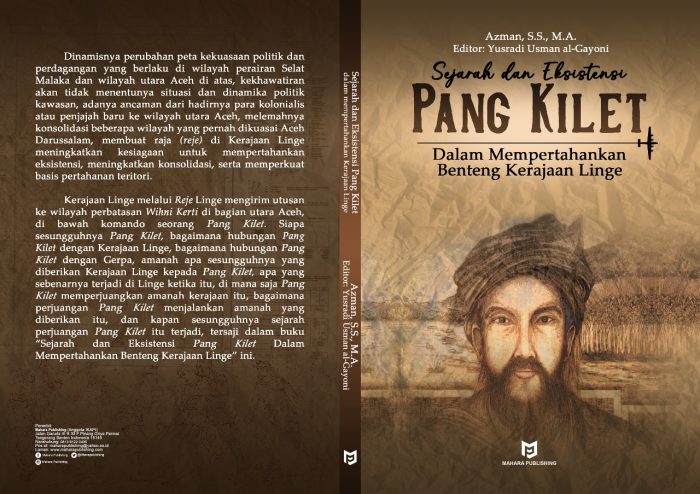Al Musanna*
MASYARAKAT Gayo adalah salah satu suku asli yang mendiami provinsi Aceh, khususnya berada di dataran tinggi Gayo (Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues dan Aceh Tenggara) dan menempati posisi kedua sebagai suku asli terbesar di Aceh. Berdasar perkiraan bahasa Gayo digunakan sekitar 260.000 orang (Eides, 2005: 3; Eades dan Hajek, 2006: 107). Dalam Grammar of Gayo: A Language of Aceh Sumatera dikemukakan bahwa bahasa Gayo termasuk keluarga bahasa Austronesia (Nias, Mentawai, Enggano, dan Batak) dan sebagian besar kosa katanya atau sekitar 40 persen secara leksikal berasal dari bahasa Melayu (Eades, 2005: 5; Melalatoa, 1982: 56).
Masyarakat Gayo (urang Gayo) mempunyai hubungan genealogis dengan orang Melayu Tua. Dalam Aceh Sepanjang Abad, Said (1985: 76) mengemukakan bahwa nenek moyang orang Gayo berasal dari Melayu Tua yang menyingkir dari pesisir pantai ke pedalaman disebabkan kedatangan Melayu Muda dari Indo-Cina dan Kamboja pada tahun 300 SM. Mereka menetap di sepanjang pantai utara dan timur Aceh dan di sepanjang aliran sungai Jambo Aye, Peureulak, dan Kuala Simpang.
Seorang pemakalah Seminar Temu Budaya Nusantara pada Pekan Kebudayaan Aceh Ke-3 Tahun 1988 mengemukakan, “…sebelum orang Aceh yang berasal dari Campa tiba di Aceh, kawasan ini didiami suku-suku lain dari Austronesia, misalnya orang Gayo, di samping bangsa Mantir (Mente) yang tergolong dalam rumpun Mon Khmer” (Ibrahim, 2007: 8). Hikayat Raja-Raja Pasai (ditulis tahun 1814 M.) merupakan literatur tertua yang mendeskripsikan pola hidup sekelompok orang yang mendiami dataran tinggi ini (diyakini sebagai leluhur suku Gayo) dan telah mengembangkan pola bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Bowen, 1993: 54).
Berdasar narasi yang berkembang luas di kalangan masyarakat Gayo (kekeberen), kerajaan pertama dikawasan tersebut didirikan Genali yang datang dari Rum (Turki) sekitar abad X Masehi (Melalatoa, 1982: Gayatri, 2008: 90). Menurut versi ini, Raja Linge sudah berhubungan dengan raja Johor melalui pengiriman hadiah dan utusan, bahkan raja Linge menikahi putri raja Johor. Rombongan pengiring putri kerajaan Johor yang terdiri dari 30 orang, akhirnya tinggal di Gayo dan diberi gelar Cik, Kejurun, Reje dan Penghulu. Dengan bertambahnya penduduk, kerajaan Linge dipecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu kerajaan Bukit di sekitar Danau Laut Tawar, kerajaan Serule, kerajaan Syiah Utama, bahkan meluas hingga daerah Batak Karo di Sumatera Utara dengan kerajaan Sibayak Lingga, dan di Sumatera Barat dengan kerajaan Wi Apuk dan Bedagai (Gayatri, Ed., 2008: 90).
Setelah berdirinya kerajaan Islam Pereulak dan terjadinya serbuan kerajaan Sriwijaya pada tahun 986 M, adik Sultan Peureulak yang bernama Malik Ishak bersama pelarian politik lainnya yang berjumlah sekitar 300 orang menetap dan diberi hak mendirikan kerajaan Islam di Isaq (45 Kilometer dari ibukota Aceh Tengah yang sekarang), yang kemudian bernama Kerajaan Malik Ishaq (Syukri, 2007: 91; Ibrahim, 2007: 1).
Kajian mengenai eksistensi masyarakat Gayo telah dimulai sejak awal abad ke-20 oleh kolonial Belanda sebagai bagian dari strategi militer melumpuhkan perjuangan rakyat Aceh. Orientalis kenamaan dan sekaligus penasehat kebijakan politik Belanda, C. S. Hourgrounje dipandang sebagai peletak kajian mengenai suku Gayo (Melalatoa, 1982). Tulisan Hourgrounje mengenai masyarakat Gayo dipublikasikan pertama kali tahun 1906 berjudul Het Gayoland en Zijne Bewoners, yang telah dialih-bahasakan menjadi Tanoh Gayo dan Penduduknya (1996). Peneliti lain mengenai masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah juga dilakukan Bowen (1984; 1991; 1993; 2003), yang dimulai dari studi penyelesaian disertasi antropologinya di Universitas Chicago pada penghujung 70-an dan berlanjut sampai awal tahun 80-an.
Penelitian mengenai masyarakat Gayo juga dilakukan seorang putra daerah, Junus Melalatoa. Pada tahun 70-an, Melalatoa adalah mahasiswa antropologi Universitas Indonesia dan setelah menyelesaikan studinya diangkat sebagai dosen dan guru besar etnologi di almamaternya. Melalatoa terlibat dalam penelitian dan pendokumentasian kebudayaan Gayo yang dibiayai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian dipublikasikan dalam sejumlah buku, di antaranya: Kamus Bahasa Gayo-Indonesia (1966); Kesenian Didong dan Perubahan Masyarakat di Gayo (1971); Sastra Lisan Masyarakat Gayo (1980); Kebudayaan Gayo (1982); dan disertasi Pseudo-Moiety Gayo: Satu Analisa tentang Hubungan Sosial Menurut Kebudayaan Gayo (1983). Karya-karya Melalatoa memberi kontribusi penting memotivasi kajian lebih spesifik mengenai berbagai dimensi budaya Gayo pada masa-masa selanjutnya.
Dikalangan masyarakat Gayo sendiri, terdapat beberapa penulis yang karyanya dikenal luas, diantaranya adalah A.R. Hakim Aman Pinan dan Drs. H. Mahmud Ibrahim. Pinan adalah pegawai departemen pendidikan dan kebudayaan sejak 1948 dan menjabat sebagai sekretaris Lembaga Kebudayaan Aceh (LKA) sejak tahun 1959. Aman Pinan dikenal sebagai tokoh adat Gayo dan dipercaya sebagai ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Kabupaten Aceh Tengah sejak tahun 1991 sampai meninggalnya tahun 2004. Di antara karya yang telah dihasilkan Aman Pinan adalah: Daur Hidup Gayo (1998); Hakikat Nilai Budaya Gayo (1998); 1001 Pepatah-Petitih Gayo (1993); Asal Linge Awal Serule (2002). Bersama Mahmud Ibrahim, Aman Pinan merampungkan seri buku mengenai Syariat dan Adat Istiadat Gayo sebanyak tiga jilid (Ibrahim dan Pinan, 2002; 2003; 2010). Sejumlah penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi juga dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perhatian mengenai aspek-aspek kearifan masyarakat setempat, meskipun lebih banyak lagi aspek kearifan yang belum terungkap dan sebahagian diantaranya hilang tergerus perkembangan zaman.
Kearifan Lokal masyarakat Gayo
Sebagai entitas sosial yang dinamis, masyarakat Gayo mengkonstruksi kearifan lokal sebagai pandangan-dunia (world-view) dalam memaknai realitas (Bowen, 1991: 4). Kearifan lokal yang merupakan representasi budaya sebuah komunitas diartikulasikan baik dalam wujud kasat mata (tangible) maupun yang tidak kasat mata (intangible). Dalam klasifikasi sejumlah pakar, setidaknya terdapat lima kategori kearifan lokal: pertama, kearifan yang berupa pandangan hidup (filosofi); kedua kearifan berupa sikap hidup sosial, nasihat dan iktibar yang diungkap dalam bentuk pepatah, perumpamaan, pantun syair atau cerita rakyat (folklor); ketiga, kearifan dalam seremoni atau upacara adat; keempat, kearifan berupa prinsip, norma, dan tata aturan yang berwujud menjadi sistem sosial; dan kelima, kearifan berupa kebiasaan, prilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial (Rasyidin, Siregar dan Batubara, dalam Afif, Bahri dan Saeful, Ed., 2009: 236).
Dalam konteks masyarakat Gayo, kearifan lokalnya terangkum dalam konsep ¨ed¨et atau adat, yang meliputi praktik, norma, dan tuntutan kehidupan sosial yang bersumber dari pengalaman yang telah melalui islamisasi (Bowen, 2003: 29). Wujud kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Gayo meliputi bahasa Gayo, sistem tata kelola pemerintahan (sarakopat), norma bermasyarakat (sumang), ekspresi estetik (didong), konsep nilai dasar budaya Gayo, dan lain-lain (Ibrahim dan Pinan, 2010; Melalatoa, 1982).
Dimensi kearifan lokal dalam masyarakat Gayo terangkum dalam nilai dasar budaya yang merepresentasikan filosofi, pandangan hidup dan karakter ideal yang hendak di capai. Merujuk klasifikasi Melalatoa terdapat tujuh nilai budaya Gayo, dimana terdapat satu nilai puncak yang merupakan representasi kearifan lokal yang berbasis nilai-nilai Islami.
Sistem nilai budaya Gayo menempatkan harga diri (mukemel) sebagai nilai utama. Untuk mencapai tingkat harga diri tersebut, seseorang harus mengamalkan atau mengacu pada sejumlah nilai penunjang: tertip (tertib/patuh pada peraturan), setie (komitmen), semayang-gemasih (simpatik), mutentu (profesional), amanah (integritas), genap-mupakat (demokratis), alang-tulung (empatik). Untuk mewujudkan berkembangnya ke-tujuh nilai penunjang perlu nilai penggerak, yang menurut Melalatoa (1982) disebut semangat kompetitif melakukan kebaikan, bersikekemelen. Berikut dikemukakan penjelasan singkat mengenai sistem nilai ini.
Mukemel
Konsep mukemel berkenaan dengan harga diri. Istiah kemel pada dasarnya berarti malu. Dalam aplikasinya malu dipahami dalam makna yang lebih luas, sehingga mencakup makna harga diri atau iffah dalam konsep studi akhlak. Konsep ini merujuk pada kemampuan menjaga diri agar tidak terjerumus pada pikiran dan tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya harga diri. Seorang yang mempunyai sikap mukemel konsisten mempertahankan harga diri dengan mencegah diri atau keluarganya terjebak pada perbuatan-perbuatan tercela atau bertentangan dengan tuntunan agama (syariat) dan norma kebiasaan (adat).
Tertib
Kata ini berasal dari bahasa Arab, tartib, artinya teratur atau berurutan. Dalam konsep fiqh, istilah tertib berkenaan dengan syarat dan rukun dalam pelaksanaan ibadah, di mana tidak terpenuhinya syarat ini dapat membatalkan atau paling tidak mengurangi kesempurnaan pelaksanaan ibadah. Dalam konteks masyarakat Gayo, tertib berkenaan dengan sikap hati-hati sehingga tindakan dan perlakukan dilakukan dengan memperhatikan konteks. Salah satu ungkapan bahasa Gayo menyatakan, tertib bermejelis, umet bermulie (artinya, keteraturan dalam kehidupan bersama merupakan prasyarat mewujudkan kemuliaan umat). Ungkapan ini menegaskan bahwa dalam sebuah komunitas yang beragam; baik ditinjau dari keahlian, minat, kecenderungan, pengalaman dan perbedaan usia diperlukan tata tertib yang dapat mengatur terwujudnya harmonisasi sosial.
Setie
Setie artinya mempunyai komitmen, teguh pendirian atau setia. Kata ini merujuk pada sikap yang tidak mudah menyerah demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini. Komitmen bersama yang disepakati dalam musyawarah misalnya, memerlukan keteguhan sikap dalam mewujudkannya. Dalam ungkapan Gayo disebutkan, setie murip, gemasih papa, yang menegaskan kesetiaan pada komitmen bersama merupakan kunci penyelesaian seberat apapun tantangan yang ada. Dalam ungkapan lainnya disebutkan, ike jema musara ate, ungke terasa gule. Ike gere musara ate, bawal terasa bangke, ungkapan ini bermakna, kalau hati sudah sepakat sepahit apapun tantangan yang menghadang mudah diselesaikan, sebaliknya apabila tidak terdapat komitmen bersama persoalan kecil dapat memicu munculnya masalah baru yang lebih besar.
Semayang-gemasih
Nilai budaya Gayo dalam konsep semayang-gemasih, artinya kasih sayang. Konsep ini berkaitan dengan prilaku terpuji dalam Islam, bahkan dua nama Allah yang baik (asmaul husna) dalam al-Qur’an adalah Maha Pengasih (al-Rahman) dan Maha Penyayang (al-Rahim). Dalam ungkapan bahasa Gayo, nilai semayang-gemasih ini tercantum dalam pribahasa; kasih enti lanih, sayang enti lelang, yang berkaitan dengan pentingnya kemampuan bertindak proporsional dalam berkasih sayang. Kasih sayang yang tidak diiringi pengetahuan dapat merusak, misalnya terlalu memanjakan anak atau memberi disertai sikap merendahkan, pamer atau penyesalan tidak akan mencapai taraf kesempurnaan kasih sayang (Ibrahim dan Pinan, 2010: 28).
Mutentu
Nilai budaya mutentu berarti rajin, ulet, bekerja keras atau melaksanakan sesuatu sesuai aturan (rapi). Nilai ini memberi penekanan pada pembentukan sikap tidak terburu-buru atau ceroboh, tetapi berdasarkan perenungan dan perencanaan yang matang. Sifat ini merupakan indikator sangat penting dalam menilai karakter dan mempengaruhi kepercayaan orang lain. Seseorang yang terlanjur melakukan perbuatan yang mencederai kepercayaan yang diberikan kepadanya akan cacat status sosialnya dalam pergaulan.
Amanah
Amanah berasal dari bahasa Arab, yang artinya terpercaya, jujur dan bertanggungjawab. Amanah berkaitan dengan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, keselarasan antara idealitas dan realitas. Sifat amanah dibuktikan oleh kemampuan seseorang menunaikan tugas atau kepercayaan yang diembankan secara bertanggungjawab, persesuaian ucapan dan perbuatan, menegakkan keadilan, ikhlas dan jujur, mengendalikan hawa nafsu (Ibrahim dan Pinan, 2010).
Genap-Mupakat
Genap-mupakat atau keramat-mupakat merupakan nilai budaya Gayo yang berkaitan dengan perwujudan harmoni sosial. Genap-mupakat merupakan pengejewantahan prinsip musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Hurgronje (1992: iv) menyatakan bahwa masyarakat Gayo mempunyai karakteristik sebagai orang republik yang bebas dan berani mengungkapkan pendapat tanpa terlalu terikat hierarki kekuasaan, sebagaimana berlaku dalam masyarakat feodal. Dalam perspektif masyarakat Gayo, penggunaan musyawarah merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup publik.
Alang-Tulung
Nilai budaya Gayo lainnya adalah sikap tolong-menolong, sebagaimana tercermin dalam ungkapan alang-tolong berat-berbantu. Nilai ini menegaskan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi sosial yang memungkinan proses memberi dan menerima (give and take, bukan take and give sebagaimana sering disebut) sebagai perekat kohesi sosial.
Bersikekemelen
Untuk mengaktualisasi sitim nilai-nilai budaya Gayo, Melalatoa (1982) mengungkapkan kemestian adanya nilai penggerak, bersikekemelen atau sikap kompetitif dalam mengamalkan ke tujuh nilai penunjang, dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Melalui nilai bersikekemelen, nilai-nilai lain akan lebih kokoh keberadaannya. Prinsip perlombaan dalam melakukan kebaikan ini mencakup pada upaya untuk meningkatkan martabat kehidupan, misalnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, perbaikan taraf ekonomi dan bahkan dalam mengamalkan ajaran agama. .”(win_moes@yahoo.co.id)
*Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Gajah Putih Takengon