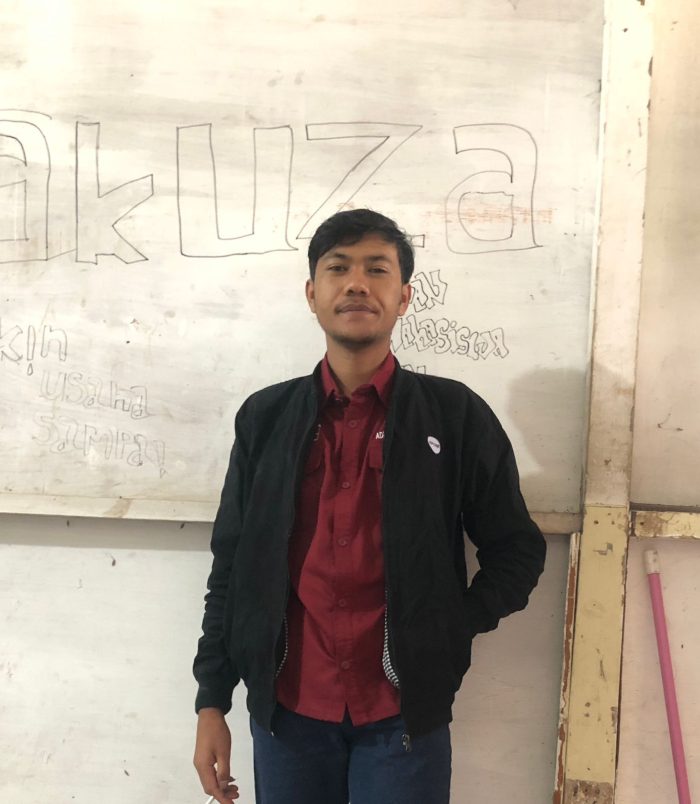SEJARAH masa lalu bangsa Gayo yang gemilang merupakan kebanggaan bagi generasi hari ini. Namun tentunya, kebanggaan tersebut tak sekadar pelipur lara ditengah ketertinggalan Gayo dibandingkan dengan kemajuan wilayah lain di Aceh.
Karena realitas faktual yang ada hari ini sangat kontradiktif bila dibandingnkan dengan kecemerlangan peradaban Gayo masa lalu. Di mana realitasnya hari ini, dataran tinggi Gayo merupakan salah satu wilayah di Aceh yang mengalami ketertinggalan dalam segala aspek kehidupan; baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik hingga sosial budaya. Ketertinggalan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal sebagai implikasi dari politik diskriminatif elite pemerintahan Aceh yang di hegemoni oleh suku Aceh pesisir.
Tapi juga dipicu oleh faktor internal bangsa Gayo sendiri yang larut dalam euphoria kegemilangan sejarah masa lalu, sementara kompetensi global menuntut kita untuk senantiasa adaptif dan responsif dengan perkembangan dunia yang kian dinamis. Kondisi bangsa Gayo hari ini bisa di analogikan sebagai pelari yang terlena dalam merayakan kesuksesannya, sementara pelari lain yang belum menang terus giat berlatih. Ujungnya, dalam perlombaan selanjutnya, bangsa Gayo menjadi tertinggal oleh bangsa yang giat berlatih tersebut.
Filosofi berlari
Perihal filosofi berlari ini bisa kita temukan dalam novel Haruki Murakami sebagaimana yang dikutip Alfan Alfian, When I Talk About When I Talk About Running (2008). Murakami tertarik pada pertanyaan apa mantra atau doa khusus bagi seorang pelari sehingga ia bisa jadi juara. Tidak ada! Yang ada bagi seorang pelari pain is inevitable, suffering is optional. Bersakit-sakit tak terhindarkan, menderita itu biasa. Itulah disiplin yang ditunjukkan dengan tiada hari tanpa latihan.
Novel Murakami ini paling tidak punya korelasi untuk mendeskripsikan kondisi suku Gayo saat ini. Karena kegemilangan peradaban Datu kita zaman dahulu bukan lahir dari ruang hampa, tapi melalui proses “berlari” dengan semangat juang dan disiplin yang tinggi.
Sementara kita yang seyogianya tinggal terus “berlari” untuk melestarikan kegemilangan tersebut justru ternina-bobokan oleh romantisme kegemilangan nenek moyang di masa lalu. Padahal suku lain, katakanlah Aceh mengencangkan ikat pinggang dengan giat berlatih. Dan terbukti hari ini, suku Aceh menjadi terdepan sementara suku Gayo terseok-seok mengejar ketertinggalan.
Sudah menjadi hukum alam bahwa siapa yang bergerak maka ia akan survive berlaga ditengah kompetensi dunia yang kian ketat. Sementara yang tidak bergerak maka ia akan mati. Karena itu bangsa Gayo harus terus berlari, jangan lagi sekadar berkutat dengan simbol-simbol kejayaan masa lalu. Karena simbol-simbol itu akan bermakna dan menjadi energy positif ketika kita senantiasa bergerak mengimbangi derasnya gelombang kompetensi global. Kuncinya, jangan cepat merasa puas dengan capaian kesuksesan yang di raih, tapi harus terus bergerak dan berkreasi.
Pun, penemuan situs purbakala (fosil kerangka manusia) berusia 7.400 tahun di Loyang Mendale, Kebayakan Aceh Tengah yang diprediksi sebagai nenek moyang bangsa Gayo dan sebagai indikasi bahwa suku Gayo adalah bangsa pertama yang mendiami negeri Aceh harus dijadikan sebagai spirit untuk bergerak, bukan untuk larut dalam euphoria romantisme sejarah.
Untuk itu, agar menjadi bangsa yang kuat “berlari” dalam mengarungi kompetensi global yang makin kompentetif, urang Gayo harus berdiri diatas kaki sendiri. Kemandirian merupakan kunci utama untuk merdeka dalam menentukan sikap. Sekali kita menggantungkan “kehendak bebas” kita pada pihak lain, maka selamanya kita akan menjadi bangsa yang terbelenggu.
Catatan penutup
Sebagai catatan penutup, kita menaruh harapan kepada pihak penyelenggara Konferensi Internasional Kerajaan Linge Gayo (ICGK-I) di Kedah Malaysia tanggal 7-9 Oktober lalu, agar kalau bisa, penyelenggaraan konferensi dimasa mendatang bisa di laksanakan di Indonesia atau di Gayo. Mungkin pelaksanaan kegiatan tersebut di Malaysia melalui pertimbangan yang matang oleh pihak penyelenggara, tapi tak menutup dugaan (dalam konteks geostrategic dan geopolitik) bahwa pelaksanaan kegiatan konferensi di negeri Jiran ini tak terlepas dari ada upaya Malaysia didalamnya untuk “menjinakan” bangsa Gayo agar lebih tunduk kepada kepentingan Malaysia daripada kepentingan Indonesia.
Hal ini bisa di lihat pada suku Aceh yang mulai “takluk” dengan irama politik “Melayu” Malaysia. Padahal, boleh jadi tujuan utamanya untuk menguras kekayaan alam Aceh untuk diangkut ke negeri Jiran. Ingat dengan kisruh antara perusahan kelapa sawit milik pengusaha Malaysia dengan masyarakat Aceh. Bahkan ada indikasi, bahwa rata-rata perusahan kelapa sawit di wilayah Sumatera adalah milik saudagar Malaysia. Dan kecendrungannya, perusahan milik pengusaha Malaysia tersebut sering bermasalah dengan masyarakat sekitar. Jadi jelas, ada upaya serius dan sistematik Malaysia untuk menguras kekayaan alam Indonesia dengan membonceng isu etnis (Melayu).
Kalau kegiatan konferensi ini bisa dilaksanakan di Indonesia, maka Saya pikir akan lebih konstruktif hasilnya. Karena kita bisa mengabarkan ke seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di Aceh ada Gayo yang memiliki khasanah budaya yang memesona, panorama alam yang eksotis serta kekayaan alam yang melimpah ruah. Bahwa bangsa Gayo juga adalah penyangga terakhir NKRI disaat Belanda menawan para pemimpin Republik. Di mana melalui siaran Radio Rimba Raya, masyarakat mondial tahu bahwa Indonesia itu masih ada dan tidak takluk kepada penjajah.
Dan yang juga sangat penting adalah bahwa Gayo merupakan salah satu suku tertua di Republik ini. Jadi masyarakat Indonesia akan tahu kondisi yang sebenarnya. Karena Saya punya pengalaman, dimana sewaktu Saya pulang ke NTT tahun 2011 lalu, ada pemahaman yang keliru dari masyarakat Indonesia soal kopi Gayo, kalau sebut kopi dari Sumatera maka yang ada dalam benak mereka adalah kopi Aceh dan Medan.
Mereka juga tak tahu kalau tarian Saman itu adalah punya urang Gayo, yang mereka tahu Saman itu adalah tarian orang Aceh. Hal ini terjadi sewaktu saya berdiskusi dengan teman (mahasiswa) di Jakarta, Denpasar, Makasar, Mataram dan Kupang.
Sehingga dengan diselenggarakannya kegiatan konferensi ini di Indonesia, maka kita bisa memosisikan dan mewartakan identitas Gayo secara benar di publik Indonesia, tanpa terbenam dalam bayang-bayang bangsa Aceh (pesisir). Namun diatas itu semua, pelaksanaan konferensi di Malaysia ini patut di beri apresiasi. Karena kegiatan ini merupakan refleksi permulaan dalam meneguhkan eksistensi bangsa Gayo. Namun alangkah baiknya kalau di mulai dari “rumah” sendiri, agar urang Gayo tak terasing di negerinya sendiri.
Untuk itu, kita harus mandiri dalam menentukan sikap. Dan yang juga tak kalah urgen adalah membangun ruang diplomasi yang setara dengan pihak manapun. Sehingga tetap survive dengan identitas sebagai bangsa Gayo. Mari terus berlari!.(Catatan: persoalan kepentingan Malaysia diatas saya kembangkan dari analisa Win Wan Nur).(for_h4mk4[at]yahoo.co.id)
*Analis Sosial & Politik