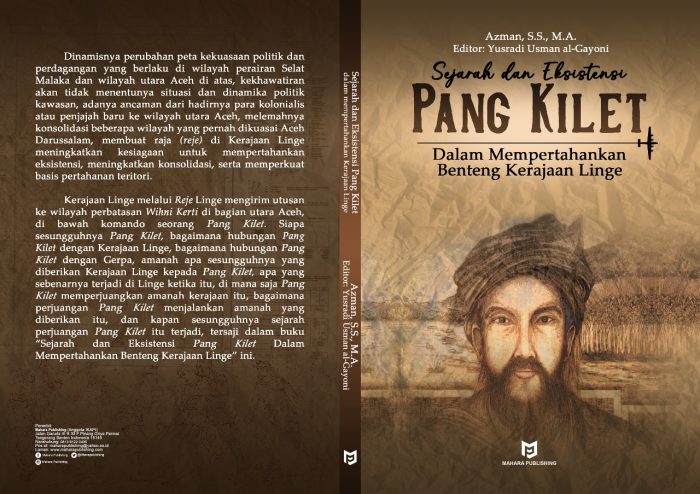Oleh: Muhammad Nasril

Diskusi mengenai persoalan mas kawin (mahar) selalu menarik untuk dibahas, bahkan akhir-akhir ini antusiasme warga di media sosial sangat respon dan aktif men-share artikel (tulisan) tentang mahar. Seperti sebuah tulisan “Mahalnya meminang perempuan Aceh”, kemudian sebagai penyeimbang munculah tulisan Jika “Perempuan Aceh “Mahal” apa kemudian pria merugi?” Kemudian saya mencoba melihat persoalan tentang mahar, ada bermacam-macam latar belakang penulisannya, yaitu pertama dikarenakan sentimen dan kedua memang ingin membagi tentang pengalaman pribadi dan isi hati atau latar belakang lainnya. Namun yang pasti dan harus diingat mahar itu wajib hukumnya, hanya kadarnya (jumlah) yang berbeda-beda. Tidak seragamnya mahar dalam masyarakat menunjukkan bahwa mahar ini sifatnya kondisional, tergantung siapa, dimana dan bagaimana kesepakatan antara kedua pihak keluarga yang akan menikah. Oleh sebab itu perbedaan ini bukanlah hal untuk diperbedatkan, hanya saja mengenai mahar ini yang perlu diketahui adalah besarnya tidak memberatkan calon linto baro (pengantin pria) sehingga batal atau gagal menikah hanya karena tingginya mahar yang diminta oleh dara baro (mempelai wanita).
Melihat kondisi hari ini, jangan sampai terkesan nikah itu sulit, suram, payah hanya karena tingginya mahar. Apalagi harga emas sekarang naik drastis, walaupun terkadang harganya turun tapi tidak sebanding dengan kenaikannya. Bagi yang belum menikah tentu menjadi hal yang menarik untuk memperhatikan harga emas untuk dijadikan “mahar“ dan rasa khawatir akan kesanggupan untuk membelinya selalu ada. Bahkan masalah ini menjadikan pernikahan bagaikan sesuatu yang menakutkan, karena kecemasan tidak bisa membawa (memenuhi) emas sebagai mahar.
Jika kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, susahnya mendapatkan emas (mahar) menjadi salah satu halangan atau kendala bagi seseorang yang hendak menikah, yang menjadi pertanyaan adalah ‘apakah kesanggupan untuk memberi mahar yang banyak termasuk dalam kategori “mampu” untuk menikah ?”. Mungkin jawaban kita “iya”, jika laki- laki sudah memiliki emas atau sanggup untuk membeli emas untuk mahar, itu akan dikategorikan sebagai laki- laki yang sudah siap ataupun mampu untuk menikah, terlepas emas itu didapatkan melalui cara apa, apakah kredit, utang, bahkan bagi PNS “SK”-nya pun disekolahkan di Bank, yang penting emas harus ada dan siap melaksanakan Aqad nikah, tanpa memperdulikan kehidupan setelah akad nikah.
Menurut hemat penulis, tingginya mahar yang disanggupi bukanlah menandakan bahwa seseorang telah siap untuk menikah, tapi lebih kepada kesiapan “palsu” atau “semu” bagi yang mendapatkan emas dengan cara kredit atau utang. Selain mahar ada hal yang lebih penting dalam sebuah pernikahan yaitu komitmen antara kedua mempelai setelah menikah dalam mengarungi serta membina rumah tangga dan juga tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing- masing.
Terlalu sulit untuk mengumpulkan emas yang banyak sehingga menjadi penghalang bagi yang hendak menikah adalah hal yang sangat disayangkan, apalagi kesiapan lainnya telah mantap, seperti kesiapan mental, pekerjaan dan ilmu karena justru hal tersebut lebih penting dari pada kesiapan memberikan “mahar” yang tinggi. Mahar tidak harus memberatkan, atau bahasa lain mahar tidak harus dengan emas. Jika pun mahar itu harus tetap emas janganlah sampai memberatkan, dikarenakan dalam sebuah pernikahan juga akan dilaksanakan resepsi atau “walimah“ yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadikan pemikiran bahwa pernikahan sulit dan berat.
Mahar “emas“ di daerah (Aceh) kita ini identik dengan “gensi“ , karena merasa bangga jika saat akad nikah mahar disebutkan dengan jumlah yang banyak, Tanpa mengedapankan rasio kita untuk tidak berpura-pura. Dalam pernikahan yang penting adanya mahar, bukan yang penting adanya emas atau mahar yang banyak. Mahar itu boleh dari sesuatu yang lain selain emas yang penting berharga atau bernilai dan adanya kerelaan antara kedua mempelai.
Kalaupun kita sepakat didaerah kita mahar itu emas, kiranya banyaknya emas yang diminta sebagai mahar tidak memberatkan dan tidak menjadi beban bagi calon pengantin pria. Membina sebuah keluarga tidak hanya diukur dari materi saja, jadi tidak perlu khawatir dengan pernikahan yang maharnya murah. Ada hal yang lebih penting yang menjadikan tolak ukur yaitu keiklasan dan tanggung jawab, bukan mengukur dari banyaknya emas sebagai mahar karena “Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).”
Mahar adalah harta atau pekerjaan yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai pengganti, dalam sebuah pernikahan menurut kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, atau berdasarkan ketetapan dari si hakim. Para ulama telah sepakat bahwa mahar hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, baik mahar tersebut disebutkan atau tidak disebutkan sehingga si suami harus membayar mahar mitsil (mahar sesuai dengan standar keluarga wanita atau sesuai mahar ibu dari wanita yang dinikahi).
Pernikahan yang tidak memakai mahar tidak sah Meskipun pihak wanita telah ridha untuk tidak mendapatkan mahar, jadi mahar tetap harus ada walaupun tidak dibayar dengan tunai. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita semisal dirinya. Kita perlu mengulang bahwa sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah, tidak mempersulit atau mahal. Memang mahar itu hak wanita, tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi sehingga menjadikan kendala bagi yang mau menikah dan dikhawatirkan terjadinya perbuatan “fahisyah“ (keji atau jelek seperti zina).
. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari’at Islam. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Sedangkan mengenai batas minimal mas kawin, para ulama mengatakan bahwa berapa saja jumlahnya selama itu berupa harta atau hal lain yang disamakan dengan harta dan disetujui serta direlakan oleh si calon mempelai wanita, maka hal demikian boleh-boleh saja.
Kita tidak terpaku dengan adat yang membuat mudharat dan semakin membebankan diri, dan adat tersebut haruslah sesuai dengan kondisi dan waktu, kita boleh mengikuti adat tapi jangan sampai menjadi beban untuk manjalankan sunnah Rasul sehingga maksiat lebih menonjol. Perbedaan daerah di aceh tentu memiliki adat yang berbeda, di Aceh secaa umum diputuskan secara musyawarah kedua belah pihak calon mempelai, sehingga mahar di aceh lebih identik dengan kondisional. Menikah tidak hanya diukur dari kesiapan materi berupa mahar yang tinggi tapi tentang tanggung jawab dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bissawab.
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana IAIN
Alamat Kreung Geukuh Aceh Utara
Bekerja : Kantor Urusan Agama (KUA) Nisam