Oleh Dedy Saputra E*
Pemilihan asas demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia mengakibatkan beberapa ekses yang harus diterima masyarakat Indonesia. Ketiadaan kultur egaliter yang selama periode kerajaan nusantara direduksi oleh kekuatan-kekuatan monarki membuat masyarakat semakin bingung di era demokrasi. Ciri dari sistem demokrasi yang seyogyanya mengharuskan masyarakat menjadi egaliter, toleran, berdaya saing tinggi amat sulit diterapkan di bumi pertiwi yang telah “nyaman” dengan sistem monarki yang serba “doktriner”.
Seiring dengan itu, dialektika masyarakat dalam proses penerimaan demokrasi sebagai sistem politik seringkali tak selalu berjalan mulus. Dalam sejarahnya kita bisa pelajari bagaimana peran aktif penguasa dalam menerapkan “tafsir tunggal” dalam proses pembumian demokrasi di bumi pertiwi. Padahal, seyogyanya yang lebih memiliki inisiatif dalam melakukan pembangunan demokrasi ialah masyarakat. Namun masyarakat terkadang masih terlalu sabar diatur secara sentralistik, untuk tidak mengatakan belum faham akan peran dan fungsinya. Namun ibarat pegas yang semakin lama ditekan maka semakin kuat hentakannya, tak kurang sudah pernah dua presiden yang ditumbangkan oleh people power Indonesia yang tidak puas dengan cara maupun hasil dari pemerintahan yang berkuasa, terlepas dari berbagai intrik dan polemik yang mengelilinginya.
Puncak dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan secara mandiri bisa dikatakan terjadi pada tahun 1998 yang lebih dikenal dengan zaman reformasi. Kehendak pengaturan daerah dengan mengambil ciri khas daerah sebagai semangat dalam pembangunan daerah semakin menyeruak setelah tumbangnya orde baru yang merupakan antitesa dari semangat tersebut. Gejolak yang kian menggelora tersebut diamini oleh penguasa pada era reformasi yang memang berkeinginan untuk menuruti kehendak masyarakat tersebut. Maka untuk itu pemerintah mengeluarkan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat mencabut aturan ini dan menggantikan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Seiring dengan pemberlakuan UU tentang otonomi daerah yang mengharuskan “penyeragaman” tentang pengelolaan daerah, melahirkan pertentangan dari beberapa wilayah. Aceh sebagai daerah yang terkenal memiliki khazanah tersendiri, merasa tidak terakomodir kepentingannya dalam UU tersebut bisa disebabkan karena faktor budaya, lingkungan dan sejarah. Aceh memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sejarah mencatat, dialektika idelogi untuk tidak mengatakan perebutan kepentingan yang kadang tidak dapat menghindari serangan senjata sepanjang orde baru bahkan hingga reformasi terus mewarnai hari-hari Serambi Mekkah.
MOU Helsinki, babak baru legalisasi syariat Islam di Aceh
Tepat pada tanggal 15 Agustus 2005 pemerintah Indonesia bersama Gerakan Aceh Merdeka difasilitasi oleh Marti Ahtisari menelurkan suatu Nota kesepahaman yang familiar disebut MOU Helsinki. MOU ini oleh sebagian orang dianggap sebagai pintu masuk untuk memberlakukan otonomi khusus Aceh yang memiliki ciri tersendiri. Salah satu kekhususan yang disetujui oleh pemerintah pusat ialah pemberlakuan syari’at Islam di bumi serambi mekkah. Pada awalnya penerapan syari’at Islam di Aceh, tidaklah menjadi salah satu “Amunisi” yang diminta oleh pihak GAM dalam perundingan helsinki. Karena Hasan Tiro, pendiri GAM, bukanlah seorang ulama seperti Daud Beureuh yang memberontak di awal kemerdekaan RI yang memang menuntut diberlakukannya syari’at Islam di bumi serambi mekkah.
Menurut Darmansyar Djumala (2013), Legalisasi syari’at Islam hanya dijadikan “alat” baik oleh pemerintah RI maupun GAM dalam proses perundingan Helsinki. Sebagaimana diungkap diatas, bahwa hasan Tiro menggagas GAM bukanlah karena ideologi Islam, melainkan untuk membangkitkan nasionalisme Aceh dari segi budaya, geografi, etnik, bahasa, dan sejarah. Untuk tujuan utamanya pengelolaan Sumber daya ekonomi aceh yang terkenal cukup “seksi”. Namun demikian, dikarenakan Islam telah melekat lama di bumi serambi mekkah, like or dislike, secara politik, Islam harus diperhitungkan untuk memperluas radius dukungan masyarakat.
Penggunaan Islam sebagai amunisi oleh pemerintah RI saat perundingan Helsinki dapat diharapkan untuk merangkul kelompok tradisional agar tidak mendukung GAM. Dengan mengizinkan pemberlakuan syari’at Islam, pemerintah ingin menimbulkan “kesan” bahwa pemerintah pusat mengakomodasi kehendak rakyat aceh. selanjutnya, faktor reformasi jelas menjadi bargaining tersendiri, dimana umat Islam lebih terbuka menyurakan aspirasinya, dan ini yang coba untuk dimanfaatkan pemerintah dalam meredam konflik Aceh. yang paling politis ialah, dengan melekatkan citra GAM dengan Islam, maka akan timbul kesan bahwa GAM fanatik dengan Islam dan dekat dengan kekerasan, sehingga menjadikan lemah bargaining GAM di mata Internasional yang sedang mengalami Islamophobia.
Dengan realita seperti diatas, jelas bahwa Islam nampaknya hanya dijadikan “komoditi” baik oleh pemerintah RI maupun GAM dalam perundingan Helsinki dengan cara yang berbeda. Dengan melekatkan citra Islam terhadap GAM, maka terlihat seakan bahwa pemerintah sudah mengakomodasi keinginan rakyat Aceh, padahal apa yang digelorakan oleh Gerakan Aceh Merdeka bukanlah penerapan syari’at Islam, melainkan pemerataan ekonomi dan persamaan dalam pengelolaan sumber daya.
Media setempat mengemukakan, dalam kurun waktu belakangan, penerapan syariat Islam di Aceh jalan di tempat. Di kota besar seperti Banda Aceh, tidak lagi menerapkan pemberlakuan hukum cambuk terhadap pelanggar qanun syariat, sehingga para pelaku tidak merasa takut jika tertangkap melakukan pelanggaran (Analisa, 11/10/2013). Yang paling terlihat nyata setengah hatinya penerapan syari’at Islam di Aceh ialah, dari mulai disahkannya Materi Qanun Maisir, Khalwat dan Maisir, sampai hari ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai Hukum Acara Jinayat yang akan diberlakukan. Pemberlakuan hukum formiil tersebut hanya didasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Demokrasi Deliberatif, sebuah keniscayaan
Dalam perspektif demokrasi deliberatif (Budi hardiman,2008) bahwa keluarnya sebuah peraturan haruslah melibatkan warga negara. Jangan yang terjadi ialah hanya dialektika antara para elite politik sebuah wilayah. Selama ini masyarakat Indonesia memang menjadi sumber legitimasi kekuasaan yang “seakan” terlibat aktif dalam tiap proses demokratisasi di negeri ini. namun yang sebenarnya terjadi ialah, peran yang dimainkan masyarakat hanyalah peran semu yang tidak terlalu signifikan pengaruhnya untuk tidak mengatakan mengalami depolitisasi. Proses demokrasi yang seharusnya memberdayakan, malah justru memperdaya masyarakat.
Kasus penerapan syari’at Islam di Aceh jika kita pandang dari kacamata demokrasi deliberatif secara nyata telah mempersempit peran serta masyarakat kepada kelompok separatis yang unlegitimate. Unlegitimate bukan hanya dari kacamata hukum negara, namun juga dari realitas sosial masyarakat Aceh. perlu diketahui, bahwa Aceh tidaklah seluruhnya setuju dengan Gerakan Aceh Merdeka, di beberapa wilayah tengah,selatan Aceh masih amat mencintai republik. Oleh karenanya dalam penerapan syariat Islam di Aceh, karena prosesnya jauh dari melibatkan masyarakat, hasilnya masyarakat tidak terlalu patuh terhadap penerapan syariat Islam. Ditambah lagi dengan setengah hatinya aparat pemerintahan Aceh menjalankan syariat, membuat syariat hanyalah sebagai kosmetik yang indah untuk menutupi jerawat.
Tidak seharusnya nilai-nilai luhur islam dijadikan komoditas politik sesaat, karena ajaran Islam sejatinya memiliki keluhuran karena merupakan wahyu ilahi. Sudah patut kiranya dipertimbangkan secara cerdas dan matang oleh para pemangku kepentingan untuk tidak sembarangan melegalisasi syariat untuk kepentingan semu. Selain itu pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan haruslah semakin ditingkatkan, jangan lagi ada represi atas opini masyarakat yang kurang sejalan dengan opini penguasa yang justru dapat mencederai kehidupan berdemokrasi di bumi pertiwi.
Penulis adalah Putra Daerah Kabupaten Bener Meriah


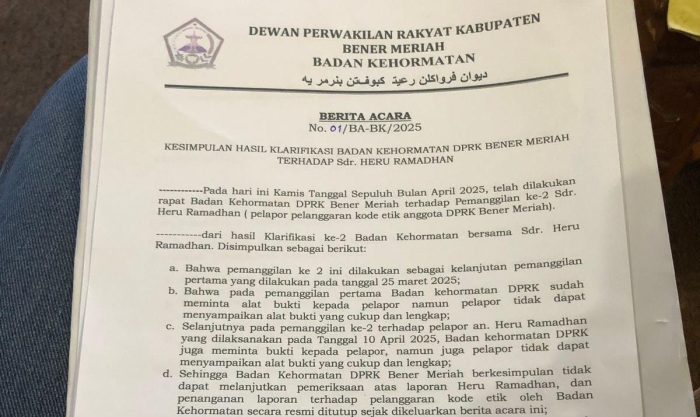






kebebasan berpikir dan subjetivitas tidak akan menimbulkan permusuhan jika penegasan hukum-hukum islam di trasnformasikan dalam leagalisasi berkehidupan bernegara….
Demokrasi bukanlah sebuah sistem super yang bisa menyelesaikan permasalahan apapun dalam bernegara.
Sebagaimana sistem pemerintahan manapun membutuhkan syarat-syarat tertentu untuk bisa sukses diterapkan di sebuah negara atau masyarakat.
Demokrasi sukses di Barat, karena masyarakat mereka memang sudah matang secara intelektual dan mental untuk berdemokrasi.
Boleh saja Budi hardiman mengatakan demokrasi deliberatif dimana keluarnya sebuah peraturan haruslah melibatkan warga negara. Jangan yang terjadi ialah hanya dialektika antara para elite politik sebuah wilayah. Tapi jelas di sini Budi hanya menghafal teori, tanpa memperhatikan sama sekali bahwa pelibatan warga negara dalam mengambil keputusan untuk keluarnya sebuah peraturan, membutuhkan satu persyaratan yang tidak bisa ditawar. Yaitu, warga yang dilibatkan itu memang sudah matang secara intelektual dan mental untuk berdemokrasi. Sebab mereka telah melewati proses panjang pergulatan pemikiran yang berujung pada gerakan Aufklaerung alias pencerahan.
Sementara, Indonesia termasuk Gayo dan Aceh di dalamnya, bisa dikatakan sama sekali tidak tersentuh oleh gerakan Aufklaerung. Inilah yang membedakan kita dengan masyarakat barat. Meskipun sama-sama pernah “nyaman” dengan sistem monarki yang serba “doktriner” dan sama-sama pernah menghadapi penguasa yang menerapkan tafsir tunggal. Masyarakat barat, melalui sejarahnya sudah melewati proses panjang pergulatan pemikiran sehingga menjadi tercerahkan dan siap untuk berdemokrasi. Indonesia, termasuk Aceh dan Gayo di dalamnya, tidak pernah melewati proses itu.
Sehingga ketika kita orang Indonesia (termasuk Gayo dan Aceh) diberikan kebebasan berpikir dan berbicara, mayoritas dari kita tidak mengerti batasan bagi kebebasan dalam berpikir dan berbicara. Ketika kita beradu argumen, faktor subjektivitas lah yang dominan.
Jadi meskipun Budi hardiman sebagaimana dikutip oleh Dedy Saputra E dalam tulisan yang saya komentari ini mengatakan “demokrasi deliberatif dimana keluarnya sebuah peraturan haruslah melibatkan warga negara adalah sebuah keniscayaan”. Tapi dalam masyarakat yang kebebasannya masih didasari oleh Subjektivitas, bukan objektivitas. Alih-alih membawa kebaikan, demokrasi deliberatif malah bisa menciptakan kehancuran.
Sebab yang namanya subjektivitas itu bukan saja berlainan, melainkan bisa bertentangan antara satu orang/kelompok dengan yang lain. Kebebasan berpikir dan berbicara yang dilandasi oleh subjektivitas (kepentigan) ini seringkali mengakibatkan permusuhan.