Oleh Win Wan Nur
Soal daya tarik ritual keagamaan dan adat, sebenarnya selain Bali setiap daerah di Indonesia juga memiliki ritual adat dan budaya yang sangat menarik, seperti Bali yang memiliki ritual kelahiran dan kematian, daerah lainpun begitu, Gayo suku saya misalnya.
Seperti Bali yang punya ritual khusus saat pemberian nama Bayi yang dinamakan upacara ‘telu bulanan’ , kamipun di Gayo memiliki ritual semacam itu, ‘Turun Mani’ namanya, seperti di Bali, di kampung sayapun bayi dipercaya lemah dan rawan terserang roh jahat saat baru lahir, karena itu sebelum si Bayi dianggap cukup kuat Bayi dilarang untuk dibawa keluar rumah. Dulu saat saya masih kecil kepercayaan seperti ini masih hidup di Gayo. Ritual ‘turun mani’ seperti yang saya sebutkan sering saya saksikan di kampung saya di Isaq. Bedanya jika di Bali bayi baru boleh keluar rumah saat sudah berumur 105 hari, maka di tempat saya cukup 7 hari saja.
Seperti ritual ‘telu bulanan’ di Bali yang sangat menarik buat disaksikan, ritual ‘turun mani’ di kampung saya juga menarik. ‘Turun Mani’ secara harfiah bisa diartikan turun untuk dimandikan, dan dulu*, Bayi berumur 7 hari itu dimandikan di sungai.
*Sebenarnya dibandingkan menggunakan bahasa Melayu, saya lebih suka menggunakan bahasa asli saya untuk menyebut kata ‘dulu’, karena makna kata ini dalam bahasa Gayo lebih detail dan presisi tidak seperti dalam bahasa Melayu yang kita pakai dalam berkomunikasi ini, dimana makna kata ‘dulu’ terlalu luas dan kurang bisa diandalkan untuk menjelaskan rentang waktu. Dalam bahasa Gayo kata ‘dulu’ dibagi tiga :
1. Inia artinya ‘dulu’ dalam waktu yang tidak terlalu lama, biasanya masih dalam tahun yang sama
2. Tengaha atau Tengahna artinya ‘dulu’ dalam waktu yang agak lama, beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu dan
3. Pudaha atau Pudahna artinya ‘dulu’ dalam pengertian beberapa generasi yang lalu.
‘dulu’ yang saya maksud dalam tulisan saya di atas adalah Tengaha atau kadang juga disebut Tengahna, tergantung selera si pengucap.
Karena itu supaya penggambaran saya lebih mudah dipahami detailnya berdasarkan rentang waktu, selanjutnya dalam tulisan ini dalam penggunaan terminologi kata ‘dulu’ saya akan menggunakan istilah
dalam bahasa asli saya*.
Ide ‘turun mani’ dalam budaya Gayo adalah untuk memperkenalkan realitas dunia nyata kepada bayi yang baru lahir. Dalam acara ritual ‘turun mani’ ada dua hal yang akan diperkenalkan kepada bayi.
Pertama memperkenalkan Bayi pada empat unsur (angin, air, api dan tanah) dan membiasakan bayi terhadap rasa dingin dan suara bising.
Supaya bisa dibayangkan seperti apa prosesi ‘turun mani’ di kampung saya ‘tengaha’, di bawah ini saya gambarkan prosesi selama ritual ‘turun mani’ di kampung saya.
‘Tengaha’ dan juga ‘Pudaha’, dalam setiap ritual ‘turun mani’ di kampung saya selalu kaum wanitalah yang berperan penting dalam ritual itu. Biasanya dalam ritual turun mani ada tiga wanita yang berperan penting dalam prosesi ditambah beberapa orang wanita lain yang bertugas memainkan alat musik. Perempuan pertama bertugas untuk melaksanakan setiap prosesi ritual ‘turun mani’ biasanya adalah keluarga dekat yang sudah agak berumur yang juga tinggal di kampung yang sama dengan si bayi. Wanita kedua bertugas menggendong bayi yang sedang di ‘turun mani’kan (iturun manin dalam bahasa Gayo), membuai si Bayi dalam gendongannya sepanjang ritual ‘turun mani’. Wanita ketiga bertugas membawa beras yang nantinya akan diberikan kepada wanita yang menggendong bayi, sedangkan wanita-wanita lainnya memainkan alat musik berupa canang yang dipukul bertalu-talu selama prosesi ‘turun mani’.
‘Tengaha’, orang di kampung saya menganggap perjalanan membawa bayi dari rumah menuju ke sungai, berpotensi membahayakan keselamatan si bayi. Karena alasan rawannya keselamatan si bayi itulah sejak 7 hari sebelumnya si bayi selalu ditempatkan di dekat ibunya. Tidak jarang dalam rumah yang memiliki bayi yang baru lahir diletakkan beragam jimat untuk menolak roh jahat, jimat-jimat itu digantungkan di setiap penjuru rumah. Sebab itulah perjalanan menuju ke sungai benar-benar harus dipersiapkan dengan baik, karena dalam perjalan itu bayi masih rawan diserang roh jahat maka dari itu persiapan untuk membawa bayi ke sungai harus benar-benar matang.
Ketika akan berangkat, wanita yang bertugas menggendong bayi akan mengambil sejumput kapas lalu menjepitnya dengan alat pembelah pinang yang kami sebut ‘kelati’ lalu membakarnya. Menurut apa yang dipercaya orang kampung saya pada saat itu, ‘kelati’ yang terbuat dari besi itu memberikan unsur logam yang bersifat keras sehingga bisa menahan gangguan roh jahat. Api yang membakar kapas membuat takut roh jahat yang ingin mendekat. Lalu canang yang dipukul bertalu-talu akan menjauhkan roh jahat dari si bayi. Kemudian sepanjang ritual ‘turun mani’ banyak sekali dipakai tanaman yang kami sebut ‘batang teguh’. Dalam kebudayaan kami tanaman ini dipercaya sebagai tanaman pertama yang tumbuh di planet ini. Penggunaan tanaman ini dalam ritual ‘turun mani’ dipercaya akan menguatkan si bayi. Karena itulah ketika akan keluar dari rumah di depan pintu wanita pertama yang akan melakukan semua prosesi dan wanita kedua yang menggendong bayi sama-sama menginjakkan kakinya ke atas seikat tanaman batang teguh yang diletakkan di depan pintu rumah si bayi. Lalu wanita yang menggendong bayi akan memegang payung untuk melindungi si bayi dari rumah sampai ke tepi sungai.
Setibanya di sungai, para wanita yang terlibat dalam ritual ini menghamparkan tikar berwarna-warni yang terbuat dari sejenis tanaman rawa yang kami sebut ‘kertan’ di atas batu. Kemudian wanita pertama yang bertugas untuk melaksanakan setiap prosesi ritual ‘turun mani’ menaburkan beras empat warna dengan bentuk lingkaran di atas selembar daun pisang. Di bagian tengah lingkaran diletakkan empat buah dari apa yang kami sebut ‘selensung’ yaitu lembaran daun sirih yang dibentuk menjadi bungkusan kecil berisi buah kemiri dan jeruk nipis. Daun pisang tersebut kemudian diangkat ke atas kepala si bayi, wanita pertama kemudian menyebutkan nama roh penunggu sungai lalu memutar daun pisang berisi beras dan ‘selengsung’ itu dengan arah berlawanan jarum jam di atas kepala si bayi dan menghitung dari satu sampai tujuh. Prosesi ini gunanya untuk menjauhkan si bayi dari segala penyakit dan nasib buruk yang disebabkan oleh empat unsur yang saya sebutkan sebelumnya, dalam bahasa gayo empat unsur itu kami sebut ‘anasir opat’.
Nama-nama roh yang disebutkan wanita pertama yang bertugas untuk melaksanakan setiap prosesi ritual ‘turun mani’ saat melakukan prosesi ini bisa bermacam-macam, tergantung siapa orangnya yang melakukan ritual itu. Kadang dalam ritual ini si wanita pertama menyebutkan nama-nama roh penjaga sungai. Dalam prosesi ‘turun mani’ yang lain yang disebut adalah nama empat roh yang mewakili empat unsur (anasir opat), satu di hulu, satu di hilir dan masing-masing satu di setiap tepi sungai. Dalam prosesi yang lain yang disebut dalam prosesi itu adalah nama nabi-nabi yang oleh orang kampung saya masa itu dipercaya merupakan penguasa unsur-unsur alam, mereka adalah Nabiolah Nuh penguasa kayu, Nabiolah Yakub penguasa batu, Nabiolah Yati penguasa air dan Nabiolah Kedemat penguasa tanah.
Kemudian daun pisang berisi beras empat warna dan empat ‘selensung’ itu dihanyutkan di sungai sambil mengatakan pada roh penjaga sungai “Ini anak kami, jangan ganggu dia atau kami akan menjewer kupingmu”. Setelah prosesi itu selesai barulah sekarang giliran si bayi yang menjadi sasaran ritual. Si Wanita pertama mula-mula beberapa kali melumuri tubuh si bayi dengan tepung, lalu juga beberapa kali menyiramnya dengan air jeruk purut dan kemudian dengan air sungai. Lalu wanita itu akan membelah buah kelapa di atas kepala si bayi maksud ritual ini supaya nantinya si bayi tidak takut mendengar suara petir, lalu membiarkan air kelapa membasahi wajah si bayi, maksud ritual ini supaya nantinya si bayi nantinya tidak takut pada hujan.
Kemudian si wanita pertama tadi memegang cermin di depan wajah si bayi, maksudnya untuk menunjukkan kepada si bayi NUR nya sendiri. Di Gayo pada masa itu (dan sekarangpun diantara beberapa orang tua di kampung-kampung) kami percaya bahwa manusia itu berasal dari NUR Allah dan NUR Muhammad. Cermin juga masa itu dipercaya akan memantulkan empat warna yang membentuk tubuh si bayi. Cermin yang diletakkan di depan wajah si bayi juga berguna untuk memberi kesempatan kepada empat unsur (anasir opat) dalam tubuh si bayi untuk melihat seperti apa rupa makhluk baru ini, supaya keempat unsur itu tahu bahwa makhluk baru ini adalah manusia dan karenanya harus dilindungi. ‘Pudaha’ sebelum ada cermin, dalam prosesi ini bayi dipegang menghadap ke air sungai supaya dia bisa melihat pantulan bayangannya.
Acara ‘turun mani’ ini diakhiri dengan prosesi si wanita pertama yang bertindak mewakili ibu si bayi memberikan sejumlah beras yang tadinya dibawa oleh wanita ketiga kepada wanita kedua yang selama prosesi ‘turun mani’ menggendong si bayi, beras yang diberikan ini kadang juga ditambahi dengan gula dan kelapa. Maksud pemberian ini adalah untuk memisahkan si bayi secara spiritual dari si wanita yang menggendongnya sepanjang ritual ‘turun mani’.
Pemberian ini adalah sebagai kompensasi atas resiko yang ditanggung si wanita penggendong selama prosesi ‘turun mani’ dan yang paling penting adalah untuk memisahkan si bayi dari resiko serangan roh jahat yang bisa jadi harus dihadapi oleh wanita yang menggendongnya tadi karena telah melindungi si bayi selama ritual ‘turun mani’ itu.
Begitulah prosesi ‘turun mani’ di tempat kami yang terjadi ‘TENGAHA’, berbeda dengan di Bali yang prosesi ‘telu bulanan’ tetap bisa kita saksikan sekarang bahkan juga sampai nanti. Prosesi ‘turun mani’ seperti yang saya ceritakan di atas, sekarang sudah punah dan tidak dapat lagi kita temui di Tanoh Gayo. Penyebabnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah Agama.
Jika di Bali adat adalah unsur yang dominan dalam relasi antara adat dan agama sehingga agama Hindu yang diimpor dari India ketika berhadapan dengan adat Bali, prakteknya dibuat mengikuti adat Bali yang sudah lebih dulu eksis. Sebaliknya dengan di Gayo dalam relasi antara adat dan agama, di daerah kami agamalah yang lebih dominan. Sehingga di Gayo adat hanya bisa dijalankan sejauh jika adat itu tidak bertentangan dengan Islam, agama yang kami anut.
‘Tengaha’ ritual ‘turun mani’ seperti yang saya gambarkan bisa ada, karena pada zaman itu transformasi ide-ide agama kepada warga kampung saya belum begitu mudah seperti sekarang. Saat itu buku masih jadi barang langka, televisi belum ada, informasi agama yang sampai ke warga kampung saya pada masa itu banyak bercampur atau diinterpretasikan oleh warga kampung saya dengan cara pandang kepercayaan pra Islam yang sebelumnya dianut oleh nenek moyang kami.
Interpretasi Ide Islam berdasarkan cara pandang kepercayaan lama ini contohnya adalah seperti penyebutan nama-nama nabi penguasa empat unsur dalam prosesi ‘turun mani’ seperti yang saya ceritakan tadi. Ide tentang nabi penguasa empat unsur itu adalah hasil interpretasi orang Gayo ‘Pudaha’ atas ide-ide Islam tentang nabi-nabi Allah.
Ketika menerima Ide-ide itu nenek moyang kami, orang Gayo ‘Pudaha’ yang alam pikirannya masih belum sepenuhnya lepas dari kepercayaan lama, lalu ‘mengislamkan’ ide-ide kepercayaan lama yang mereka anut dengan mengganti nama roh-roh yang dipercaya menguasai alam dengan mengganti namanya dengan nama nabi-nabi Islam. Dalam proses ‘pengislaman’ ide ini bahkan terkadang nama nabinyapun tidak kita temui dalam literatur Islam yang asli. Contohnya bisa dilihat dari nama-nama nabi penguasa empat unsur yang saya sebutkan di atas, di sana ada nama Nabiolah Yati dan Nabiolah Kedemat yang tidak kita temui dalam literatur Islam yang berasal dari Timur Tengah.
Sebagai gambaran sulitnya transformasi ide di masa yang saya ceritakan itu (sekitar akhir 1979 atau awal 1980-an, sebelum saya masuk SD), Isaq kampung saya yang merupakan ibukota kecamatan Linge, saat itu masih relatif terisolasi ide yang berkembang di Isaq lebih banyak ide-ide yang berkembang diantara orang Isaq sendiri. Orang luar seperti orang-orang Gayo yang tinggal di Takengon* (Ibukota kabutapen Aceh Tengah) misalnya masih b,anyak yang takut berkunjung ke kampung kami. Karena di Takengon banyak beredar kabar, yang juga banyak dipercaya oleh penduduk Takengon masa itu kalau penduduk kampung saya banyak yang memiliki ilmu gaib.
* Nama Kota Takengon ini sendiri, menurut analisa saya sebenarnya adalah pengindoseniaan dari nama asli kota ini yaitu TAKINGEN. Takingen disebut Takengon menurut saya adalah karena mode latah masa awal kemerdekaan, ketika orang Gayo ramai-ramai meninggalkan adat Gayo dan menggantinya dengan sesuatu yang dianggap modern dan keren di masa itu yaitu ide tentang Indonesia. Saat itu banyak nama tempat di Gayo yang di indonesiakan, Bebesen pernah diganti menjadi BOBASAN tapi tidak berlanjut, Kebet menjadi KOBAT, Kebayaken menjadi KEBAYAKAN, Janarata menjadi PONDOK BARU. Salah satu akibat atau bisa juga disebut korban dari mode latah ini adalah munculnya nama Sukur KOBAT (Maaf Cik Sukur) dan Abu TAKENGON. Meskipun pengindonesiaan itu telah dicoba dipas-paskan atau lebih tepat disebut dipaksakan dengan menciptakan cerita yang tidak jelas asal-usulnya yang menyebutkan kata TAKENGON itu berasal dari bahasa Gayo yang berbunyi beTA KuENGON, tapi yang jelas sampai hari ini saya tidak pernah mendengar ada orang Gayo yang menyebut nama kota ini dengan nama TAKENGON ketika sedang berbicara dalam bahasa Gayo. Saat berbicara dalam bahasa Gayo, orang Gayo pasti selalu menyebut nama kota ini TAKINGEN *
Zaman sekarang, ketika transformasi ide sudah demikian mudah, ide-ide keagamaan (islam) ditransformasikan demikian mudahnya, melalui buku, koran, radio bahkan televisi. Orang-orang di tanah Gayo semakin banyak yang menyadari kalau praktek-praktek ritual semacam yang saya ceritakan tadi banyak mengandung unsur bid’ah, khurafat bahkan syirik, sehingga praktek seperti itu semakin hari semakin ditinggalkan.
Saat ini saya yakin sekali kalau sudah tidak ada lagi wanita Gayo di generasi saya yang mampu melaksanakan prosesi turun mani seperti yang saya ceritakan di atas.
Wassalam
Win Wan Nur



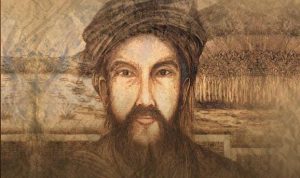


oooow…..
saya pikir Gayo itu ada hubungan atau turunan dengan bali…
trima kasih pak penjelasan nya,,,
Berdasarkan penelitian antropologi, banyak antropolog yang menggolongkan Gayo itu ke dalam salah satu dari pecahan etnik group Austronesia.
di dalam kelompok ini termasuk Jawa, Khmer, Thai, Bali, Sasak, Toraja sampai suku-suku di Philipina.
Walaikum salam Myra…
Sebelumnya terima kasih atas tanggapannya.
Soal pertanyaan Myra kenapa Bali yang saya jadikan contoh di sini, karena ritual-ritual seperti yang saya ceritakan ini adalah ritual-ritual yang berasal dari masa Pra Islam yang dulunya bisa kita temukan di hampir seluruh kebudayaan Austronesia.
Nah kenapa Bali yang saya jadikan contoh, itu karena masyarakat Bali adalah daerah yang sampai sekarang paling teguh dan paling konsisten mempraktekkan ritual-ritual yang berasal dari tradisi Pra-Islam semacam itu. Dan bukan kebetulan Bali adalah salah satu pecahan budaya Austronesia sebagaimana halnya Gayo.
Ada banyak sekali kemiripan antara Gayo dan Bali, sebut saya dari segi bahasa misalnya, ada banyak kata-kata bahasa Bali, yang pengucapan dan artinya persis seperti bahasa Gayo, sebagai contoh katakanlah kata “tasak” dan “matah”, dua kata ini memiliki pengucapan dan arti yang persis sama dengan bahasa Bali.
Tapi yang paling menarik bagi saya adalah kata ‘Ume’ yang berarti sawah ‘Ume’ dalam bahasa Bali adalah bahasa halus untuk menyebut sawah, sementara bahasa kasarnya adalah ‘carik’.
Nah kita di Gayo mungkin sudah tidak ada lagi yang paham dari mana asal-usul yang membuat mengapa sawah disebut ‘Ume’, tapi di Bali, akar sebutan itu sangat mudah ditemukan, sebutan ‘UME’ itu berasal dari kata ‘UMA’ yang dalam kepercayaan orang Bali adalah Dewi penguasa sawah. Kalau anda mengenal nama Uma Thurman, yang artis hollywood, namanya itu diambil dari nama Dewi ini, karena bapaknya senang mempelajari tradisi India.
Seperti dalam bahasa Gayo, dalam bahasa Bali, semua kata berakhiran A itu dibaca dengan E, misalnya di Gayo, ‘Gula’ menjadi ‘Gule’, kuda menjadi ‘Kude’, Bunga menjadi ‘Bunge’, di Bali juga sama,anda mungkin familiar dengan Pantai Kuta, di Bali itu disebut ‘Kute’. karena itulah ‘Uma’ disebut ‘Ume’
Maaf kalau jawabannya kepanjangan dan melantur kemana-mana.
Kereeenn…dulu juga sy pernah di desa Batur Kintamani Bangli…selintas sy dengar logat bhs Bali yg mrk bicarakan kok mirip2 dgn logat org Gayo ketika sdg berbicara. Trus kl ga salah org Bali bilang TABE utk permisi, sama dgn bhs Gayo yaitu TABI..
ass wr wb,,,
bapak,, nama sya Myra saya sangat tertarik dengan sejarah yg bpk cantumkan d atas,, stlh sy baca byk hal y baru sya tao, bahkan umur sya sdah 21 th tp sy baru tahu ternyata makna dari “belah keramil” itu u memperkenalkan bayi ttg hujan dan petir…
tpi sy mao bertanya pak knapa perbandingan nya dengan Bali??? trima kasih y pak…