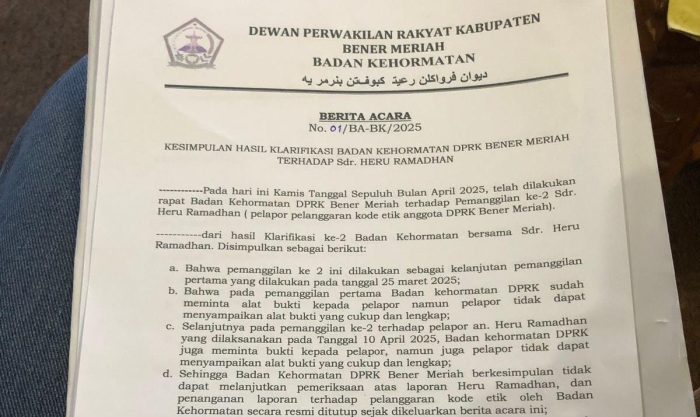“ÔNÔNG-ÔNÔNG” berarti: meniru idé, gaya (style) dan konsep orang lain oleh sesorang maupun ‘public’. Definisi sederhana ini hanya sekedar memudahkan memahami, sekaligus untuk membedakan dengan istilah “uru-uru” (bahasa gayo) yang berarti meniru suara dan ‘plagiator’ yang meniru karya tulis orang lain.
Dalam lingkaran interaksi social, prilaku meniru berlaku secara alamiah, yang pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang normal dan sah-sah saja, misalnya: meniru model potongan rambut, pakaian, mazhab musik, gaya bicara/bernyanyi, dll.; sejauh ianya tidak merugikan pemilik. Adakalanya “ônông-ônông” mengandung sesuatu yang positif,terkadang negatif; ianya tergantung pada imbas yang ditimbulkan. Yang pasti, jika tindakan meniru mengarah atau terkait dengan hak Paten tertentu, maka tindakan tidak dibenarkan (illegal) tanpa seizin dan kontrak antara peniru dan pemilik hak Paten.
Terlepas dari semua itu, dari sudut psykhologi; gejala “ônông-ônông” merupakan bentuk atau refleksi dari kelainan jiwa seseorang, ’public’ atau ‘phariah class’ yang punya kepribadian lemah dan retak, karena tidak memiliki khazanah berpikir (idé dan konsep); sehingga ’kesamun’ setiap terjadi perubahan baru (anèh) yang diciptakan orang dan serta-merta mengakui sebagai idola dan menirunya. Ini kerap terjadi dalam dunia glamor: mode, dunia film dan hiburan. Bahkan sekarang sudah masuk ke ranah kriminalitas yang melanda masyarakat di segenap pelosok dunia.
Prilaku “ônông-ônông” kerap melanda remaja yang merasa bangga punya hp atau computer model baru. Mengatas namakan ”ikut model”, mereka “ônông-ônông” membeli sebagai konsumen. Tanpa disadari, mereka adalah mangsa dari tehnologi modern milik bangsa lain. Streotype masyarakat demikian; jaringan saraf dalam otaknya tidak lagi menyimpan data memori yang merangsang untuk bersaing atau “ônông-ônông” dalam arti: sebagai pengalih tehnologi, bukan konsumen. Jaringan otaknya persis kepala udang, gudang menyimpan kotoran.
Dalam konteks ini, Cina, Jepang dan Korea Selatan –yang sebelumnya menjadi mangsa dari tehnologi Barat– merubahnya menjadi negara-negara yang menguasai alih tehnologi Barat [setelah disepakati dalam kontrak]; bukan “ônông-ônông” sebagai konsumen. Inilah jiwa atau arti lain dari pernyataan: ”wata’auwwanu ’alal birri wa taqwa” [berlomba-lomba (baca: “ônông-ônông”) dalam hal kebaikan dan taqwa]
Dalam budaya gayo; “ônông-ônông” lebih dipahami sebagai sesuatu yang pasif -setidak-tidaknya- kurang agresif dan dinamis. Hal ini dapat dibuktikan dari lirik lagu ”Masa” ciptaan group Winar Bujang, sbb:
//Ara nawè ku tepi//
(Ada yang berenang ke tepian)
//Hèk-hèk mari pecengang//
(Lelah-lelah,berhenti sambil memandang)
//Nengon paong guredi//
(Melihat kawan gembira sekali)
//Itabun diri ku berawang//
(Ceburkan diri dalam sungai)
Dari ayat-ayat Didong ini nampak bahwa, objek “ônông-ônông” sama sekali tidak menunjukkan kualitas, melainkan mengèkor dan hura-hura. Menceburkan diri kedalam sungai hanya lantaran melihat kawan gembira, bukan alasan lain, misalnya: mengapa liriknya tidak berbunyi:
//nengon waih jernihdi//
(melihat air jernih sekali)
//Itabun diri ku berawang//
(Ceburkan diri dalam sungai)?
sehingga argumennya bisa diterima oleh logika dan rasio. Setelah diamati secara cermat, masalahnya memang tidak terletak di sini. Salah satu karakter massal orang gayo adalah “ônông-ônông”. Jadi, sungguh tidak mengherankan, kalau suatu ketika dahulu: orang Gayo membabat batang kopinya dan memugar hutan, hanya lantaran tergiur mendengar harga minyak Nilam melonjak. Hampir semua petani “ônông-ônông” menanam minyak Nilam, walau akhirnya tenggelam dalam ”berawang” minyak Nilam.
Contoh lain: ketika merebak hama ”selingkuh” (berbuat serong di luar hubungan suami/isteri) -yang dilarang oleh hukum Islam (Q: Surat al-Mu’minun:7)- orang gayopun “ônông-ônông” selingkuh, yang kononnya mengikuti perkembangan zaman modern, hingga di Kabupaten Aceh Tengah tercatat lebih dari 3000 pasangan suami/isteri berselingkuh yang mengajukan gugat cerai di Mahkamah Syari’ah dalam tempo setahun {Data: tahun 2006}. Begitu pula, saat dilihatnya Aceh Pesisir berniaga; orang gayopun “ônông-ônông” berniaga, sampai-sampai jumlah kiosk dalam suatu kampung tidak seimbang lagi dengan jumlah penduduknya. Orang gayo benar-benar tukang “ônông-ônông” tanpa ilmu pengetahuan.
Apa konsekuensi dari “ônông-ônông” tanpa konsep? Yang pasti, akan melahirkan keragu-raguan dan ketidak-yakinan untuk melakukan sesuatu, seperti digambarkan dalam lirik:
//Wo kuyu alus yupkomi//
(Wahai angin semilir, terbangkanlah)
//Lelayang ku kuwen ku kiri//
(Layang-layang ke kanan ke kiri)
//So emun ijo penanti//
(Disana awan biru menanti)
//Ku unur terih ko tali//
(Ku undur tali dengan rasa takut)
Di sini, rasa takut dan ragu-ragu melilit orang yang suka “ônông-ônông” dengantiada dalih yang rasional. Lantas, bagaimana solusinya? Untuk itu, orang gayo harus merubah paradigma budaya, dari: “ônông-ônông, kusi kecip konè manung; …kusi awah konè yung; …kusi Lokot, koné Denung” kepada paradigma berpikir, yakni: ”Tabur ni burak, ooo burak… katan ni langit, gere musengkelit, sengkelit… kona ku emun”.
Kalimat: ”gere musengkelit, sengkelit…kona ku emun” harus tafsirkan dalam makna kontekstual, bukan tekstual. Artinya: orang gayo punya imaginasi tinggi, yang daya pikirnya mampu menerobos segala rintangan di darat, laut,udara dan mampu bersaing dalam lapangan ekonomi, politik dll. tanpa harus menyentuh/menyakiti perasaan orang lain. Selain itu; Orang gayo mesti merubah pola pikir, dari: ”Ike nge tangkuh Radio ayu, nguk aku mujuel bateré; atau: ike ara jema nos tahu, nguk aku mujuel témpé” kepada paradigma berpikir falsafah gayo yang menyebut:
//Kao i langit selo ku tuyuh, kaléi tubuh//
(Kau di langit, bila jatuh ke bawah, tubuh ini rindu)
//Sigé ku pasang berkité uluh, buge erôh//
(Kupasang tangga dari batang bambu bercabang, biar pas)
// Kao le bintang si malé kin suluh//
(Kau bintang akan menjadi obor).
Artinya: orang gayo; pada dasarnya bukanlah type manusia penjual bateré dan pembuat témpé; melainkan punya imaginasi, yang mampu menghubungkan antara manusia, ilmu pengetahuan dan ruang angkasa. Hubungan tersebut terlihat dalam kosa kata: ”langit”, ”bintang”, ”tubuh” (baca:manusia) dan ”sigè” (instrumen/ pengetahuan); yang semua ini bisa wujud, sekiranya manusia memiliki ”instrument” untuk mencapainya, yakni: ilmu pengetahuan, bukan ilmu “ônông-ônông”! Dalam kaitan ini difirmankan: ”Wahai jama’ah Jin dan manusia, jika kalian sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, lintasilah. Kalian tidak akan dapat melintasinya, kecuali: dengan kekuatan (ilmu pengetahuan).” (Q: surat Arrahman: 33). Akhirnya, peradaban gayo memang rencam dengan kepelbagaian nilai-nilai dan rona-rona budaya; yang di satu sisi bermental “ônông-ônông dan di sisi lain punya falsafah hidup yang agung. Akankah buat selamanya orang gayo “ônông-ônông” atau sebaliknya? Hanya kekuatan imaginasi dan kereativitas yang menentukan!
[1] . Pengasas ”Konferensi Gayo Sedunia” yang masih belum berhasil diselenggarakan