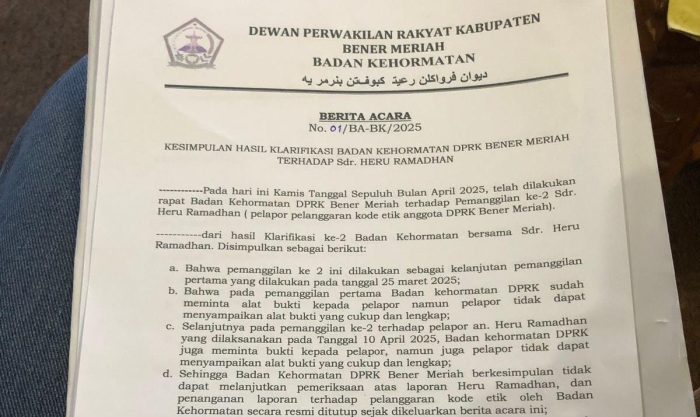Oleh :Saradi Wantona
Oleh :Saradi Wantona
Jika tidak ada perubahan, sudah dapat dipastikan pemilihan kepala daerah mulai gubernur, bupati dan walikota tahap II akan bergulir pada tahun 2017 mendatang. Pada Pilkada serentak 2017, provinsi dengan jumlah pemilihan terbanyak adalah Aceh yang akan memilih 20 bupati dan wali kota.
Dalam catatan KPU untuk periode keserentakan, Aceh adalah yang paling besar penyelenggaraan pilkada (news.okezone.com/2016/02/15. Para kandidatpun bermunculan, wajah lama, wajar baru, berusaha mengambil hati para rakyat demi sebuah kursi yang sangat istimewa.
Konon karena sangat istimewa ini kursi, bisa menghantarkan orangnya menjadi kaya raya, dan bergelimangan harta, membangun dinasti politiknya sampai tujuh keturuanannya kelak. Tapi tidak jarang pemilik kursi ini bisa sampai pindah ke hotel prodeo milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terjerat kasus korupsi.
Karena kursi ini sangat istimewa mampu mengalahkan kursi – kursi yang berjejer disetiap warung kopi. Kursi ini diklaim oleh yang duduk di sana adalah milik semua orang, meskipun sampai saat ini tidak ada yang merasa kursi ini adalah milik masyarakat. Karena, menurut pengakuan beberapa teman, kursi itu sudah dijual pada saat pemilihan di masa lalu.
Semenjak runtuhnya rezim orde baru, masa reformasi pun bergulir, pemilihan kepala daerah langsung dipilih langsung rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menjadi substansi dari makna demokrasi sesungguhnya. Belakangan, karena iklim demokrasi yang begitu melampaui sistem pemerintahan di masa lalu, kini menjadi terbuka sangat lebar yang mengatasnamakan sebuah kebebasan. Setiap orang bebas berpendapat, partisipasi dalam politik, gender dan sebagainya.
Untuk itu dalam iklim demokrasi rakyatlah yang bertanggung jawab atas apa yang telah ia pilih, seperti memilih gubernur, bupati dan walikota bahkan presiden sekalipun. Jika kepala daerah memiliki prestasi dan jejak rekam yang bagus, rakyatlah yang diuntungkan, kalau kepala daerahnya bisa membangun wilayah yang dipimpinya menjadi lebih baik, seperti pemberantasan angka kemiskinan, terbukanya lapangan kerja, orang sakit biayanya murah, hargan pangan terjangkau sampai ke semua kalangan dan sebagainya. Jika kepala daerahnya gagal mewujukan kesahteraan dan kemakmuran, tentu rakyat juga yang dirugikan.
Badan Pusat Statistik mencatat Aceh masih mendapat nomor 2 provinsi termiskin di pulau Sumatera setelah provinsi Bengkulu (Zulkifli, lintasgayo.com-2016). Belum lagi meningkatnya angka pengangguran sepanjang tahun, ini menandakan pemerintah belum mampu menciptakan program – program yang pro rakyat, mendatangkan investor dalam mengatasi masalah kemiskinan di berbagai wilayah di Aceh. Semangat membangun inilah belum terjadi pada setiap kepala daerah yang memimpin saat ini.
Rakyat hanya bisa menunggu periode berikutnya, saat pemilihan umum kembali digelar, rakyat berharap ada para kandidat yang memberikan formula baru dalam mengatasi masalah yang paling krusial saat ini “ kemiskinan “, lagi – lagi pemerintah kita lalai dalam urusan perang anggaran, perang regulasi pilkada, bendera dan lambang sampai yang paling konyol pengadaan daster beberapa tahun lalu.
Di masa lalu para pemimpin kita membangun “ bargaining” dan politik harapan yang manis dilidah realitanya bertolak belakang. Hingga kemudian pesta demokrasi akan bergulir kembali, sejumlah media massa menyajikan informasi para pejabat tentang kunjungan kerja, kegiatan ceremonial sampai satu bulan disetiap daerah, temu ramah dan sebagainya. Kita jarang menemukan capaian dan prestasi yang telah diciptakan selama lima tahun sebelumnya.
Dengan minimnya prestasi, dengan bangga dan terbuka kembali mencalonkan diri menjadi kandidat kepala daerah untuk lima tahun yang akan datang. Di era demokrasi ini adalah arena politik formal yang sangat terbuka siapa saja bisa berpartisipasi, namun demikian seharusnya kita sadar, dengan kapabilitas yang kita miliki, pantaskah masih menjadi pemimpin untuk masa yang akan datang.
Inilah bukti para pemimpin kita belum mampu membangun kesadaran bahwa arena politik adalah sebuah pergulatan perjuangan yang sangat ketat yang dominan berurusan dengan kepentingan – kepentingan rakyat secara luas. Jika sebelumnya tidak ada prestasi yang dicapai, buat apa mencalonkan diri kembali.
Di negeri China, jika ada pejabat yang menganggap dirinya tidak mampu membawa perubahan untuk masyarakat, tanpa sungkan langsung mengajukan berhenti dan digantikan oleh orang lain yang lebih mampu, di tempat kita jarang terjadi.Dengan begitu, kini penentuan ada pada masyarakat, pengalaman – pengamalan dimasa lalu seharusnya menjadi pedoman dimasa yang akan datang, pilihlah pemimpin yang memiliki jejak rekam yang kapabel, berintegritas, dan mumpuni.
Sesuai apa yang apa yang dikemukan Jean Jacques Rousseau pemikir politik asal Swiss pada abad ke-19, bahwa masyarakat harus membangun “Du Contract Social”, dengan kata lain masyarakat, memiliki kehendak penuh dalam mengelola dan menentukan pilihan dalam bernegara serta pemimpinnya. Menurut Rousseaumasyarakat dengan total bisa memerintah negara/pemimpinnya lewat kehendak umum. Dengan begitu masyarakatlah menjadi “power of kontrol” terhadap pemerintah. Di atas kertas itu teorinya, di dunia nyata ceritanya pun berbeda.
Untuk itu masyarakat, harus cerdas dalam memilih para pemimpinnya di masa yang akan datang. Rasionalisasi menjadi tolok ukur, bahwa masyarakat harus berperan aktif, menolak pemimpin yang minim prestasi dan hanya membual janji tanpa ada bukti. Dalam sejarah filsafat Yunani terdapat satu kelompok filosof yang dikenal dengan ‘kaum Sofis’ (shopistês), yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: seseorang yang menipu orang lain dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi yang tidak sah. ( Dr. K. Bertens, 83:1999).
Konon salah seorang shopist melihat seorang pemuda lalu berkata kepadanya, maukah kubuktikan kepadamu dengan akal bahwa engkau adalah keledai ?” Cobalah ! aku mendengarnya,” kata si pemuda. Shopist mengatakan, bukankah aku bukan engkau, dan engkau pun bukan aku?”. Itu benar jawab si pemuda. “ aku bukanlah keledai,” kata si pengguna akalnya itu.
“Itu benar. Tidak diragukan, engkau bukanlah keledai,” kata anak muda itu. Shopist lalu menyela,” karena aku bukan engkau, dan aku bukan keledai, jika demikian engkaulah yang keledai “. Demikian gambaran ekstrem dari seseorang yang merasa menggunakan akalnya menuduh orang lain keledai, bahkan boleh jadi lebih tepat sang penuduh itulah yang keledai. Nah !!
Saradi Wantona, S. Sos, Alumnus Sosiologi FISIP Universitas Syiah Kuala, Berdomisili di Bener Meriah.