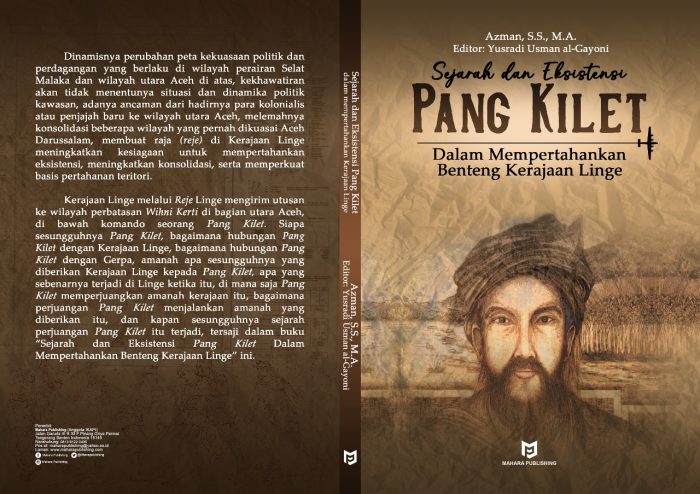Oleh : Win Wan Nur*
Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 20 Januari 2014, media ini menayangkan artikel berjudul “Legalisasi Syariat ISLAM Serambi Mekah, Politik Atau Indetitas ?”http://www.lintasgayo.com/45701/lagalisasi-syariat-islam-serambi-mekah-politik-atau-indetitas.html yang ditulis oleh Dedy Saputra E.
Dalam tulisan ini, Dedi mengkritisi tentang Ketiadaan kultur egaliter yang menjadikan masyarakat bingung dengan sistem demokrasi. Di sini Dedi menyalahkan kerajaan nusantara yang membuat masyarakat di negara ini “nyaman” dengan sistem monarki yang serba “doktriner”. Selanjutnya, Dedy menyalahkan penguasa yang menerapkan tafsir tunggal dalam pembumian demokrasi dan di akhir kesimpulannya Dedy mengutip pendapat Budi hardiman yang menyatakan bahwa demokrasi deliberatif sebagai sebuah keniscayaan.
Ada banyak hal yang bisa kita kritisi dari tulisan ini. Yang paling nyata adalah fakta bahwa bukan hanya masyarakat Indonesia. Masyarakat barat pun yang sekarang sukses dengan demokrasi juga sempat sangat lama “nyaman” dengan sistem monarki yang serba “doktriner”. Soal penguasa yang menerapkan tafsir tunggal, barat malah lebih parah mengalaminya. Peradaban barat pernah ditidurkan oleh fundamentalisme Kristen selama lebih dari SERIBU tahun, pada masa yang terkenal dengan nama Abad Pertengahan atau Abad KEGELAPAN.
Silau dengan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat barat yang berdasarkan atas sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Banyak dari kita yang kemudian berpikir bahwa demokrasi adalah sebuah sistem super yang bisa menyelesaikan permasalahan apapun dalam bernegara. Tanpa menyadari bahwa untuk bisa sukses, demokrasi juga memiliki “MUST CRITERIA”. Yaitu kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu “usaha”.
Sebagian besar dari kita menganggap bahwa demokrasi adalah manifestasi dari PEMILIHAN BEBAS (dan rahasia). Padahal anggapan ini adalah suatu kekeliruan fundamental, karena yang benar adalah: INTI dari demokrasi adalah KEBEBASAN BERPIKIR dan BERBICARA (freedom of thought and freedom of speech). Ini bisa kita lihat pada landasan UUD Amerika Serikat (Bill of Rights Amendment I)
Tapi pertanyaannya kemudian apakah bebas berpikir dan berbicara saja, bisa menjamin demokrasi akan sukses?. Tentu saja tidak. Sebab disinilah letaknya MUST CRITERIA yang disebutkan di atas.
MUST CRITERIA untuk bisa suksesnya sebuah sistem bernama demokrasi adalah keberadaan masyarakat yang memahami batas antara kebebasan pribadi dan kebebasan orang lain. Sebab meskipun judulnya dalah KEBEBASAN tapi sebagaimana hukum alam yang berlaku di dunia dimana semuanya memiliki batasan. Tanpa batasan-batasan yang jelas, Kebebasan berpikir dan berbicara hanya akan menciptakan chaos dan menimbulkan anarki.
Batasan dari kebebasan berpikir dan berbicara ini adalah kebebasan orang lain. Lalu dimana tepatnya letak batasan itu?. Pertanyaan ini menjadi perdebatan panjang yang memakan waktu ribuan tahun sejarah peradaban yang melibatkan cerdik cendekia di setiap masa, mereka yang umum disebut sebagai filsuf.
Di barat, perdebatan ini berakhir dengan tibanya masa pencerahan. Gerakan Aufklaerung atau *Enlightenment* dalam bahasa Inggrisnya. Terbitnya buku *Critique of Pure Reason* karya Immanuel Kant adalah puncak dari gerakan ini.
Dalam karyanya yang termasyhur ini, Kant mengatakan bahwa logika dan rasio manusia itu terbatas. Kant menyebutnya “kategori akal manusia” yang merupakan satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan ketika berdebat antar sesama manusia. Alasannya, logika dan rasio, terbukti SAMA bagi setiap manusia.
Dalam buku yang sama Kant juga mengatakan bahwa debat ngalor- ngidul secara verbal (PURE reason) tidak ada gunanya, sebab masing-masing pihak selalu bisa saja mencari alasan membenarkan pendapatnya sendiri dan mempersalahkan pendapat lawan. Satu-satunya nya jalan yang bisa mengakhiri perdebatan adalah OBSERVASI EMPIRIS.
Gerakan Aufklaerung inilah yang kemudian melahirkan DEMOKRASI, dan pendapat yang disampaikan oleh Kant dalam *Critique of Pure Reason* inilah yang menjadi landasan dan batasan bagi kebebasan berbicara.
Di barat, pemikiran ini kemudian diajarkan di semua sekolah dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya kenapa Demokrasi sukses di Barat. Itu karena masyarakat mereka sudah sangat fasih dan matang dalam memahami bahkan secara otomatis menghormati batasan-batasan itu tanpa perlu lagi diingatkan, karena itu semua sudah menjadi bagian dari kepribadian mereka.
Dalam masyarakat seperti ini, ketika seorang pemimpin berbicara tentang keberhasilan pemerintahannya. Dia tidak bisa menghiraukan fakta, seperti
misalnya bersikeras politik ekonominya `berhasil’, sekalipun fakta menunjukkan sebaliknya, yaitu bahwa GDP terus menurun. Seorang bupati tidak akan bisa mengatakan kebijakan transmigrasi bidang peternakannya berhasil, sementara kenyataannya lebih banyak peserta transmigrasi yang menjual ternak yang diberikan kepadanya daripada yang benar-benar serius memeliharanya.
Sementara, Indonesia termasuk Gayo dan Aceh di dalamnya, bisa dikatakan sama sekali tidak tersentuh oleh gerakan Aufklaerung. Inilah yang membedakan kita dengan masyarakat barat. Meskipun sama-sama pernah “nyaman” dengan sistem monarki yang serba “doktriner” dan sama-sama pernah menghadapi penguasa yang menerapkan tafsir tunggal. Masyarakat barat, melalui sejarahnya sudah melewati proses panjang pergulatan pemikiran sehingga menjadi tercerahkan dan siap untuk berdemokrasi. Indonesia, termasuk Aceh dan Gayo di dalamnya, tidak pernah melewati proses itu.
Sehingga ketika kita orang Indonesia (termasuk Gayo dan Aceh) diberikan kebebasan berpikir dan berbicara, mayoritas dari kita tidak mengerti batasan bagi kebebasan dalam berpikir dan berbicara. Ketika kita beradu argumen, faktor subjektivitas lah yang dominan.
Dalam demokrasi di masyarakat yang dikuasai oleh subjektifitas, siapa yang pandai bersilat lidah, dialah yang benar. Sebab berdasarkan sistem demokrasi, sebuah pendapat dikatakan benar, kalau didukung oleh banyak orang.
Tak perlu data, tak perlu pembuktian empiris yang melelahkan dan menguras segala kemampuan intelektual dan stamina. Siapa yang paling jago BER-RETORIKA, siapa yang paling pintar mengambil hati banyak orang dialah yang paling berpeluang memiliki banyak pendukung dan menjadikan pendapatnya sebagai kebenaran yang atas nama demokrasi harus diterima oleh semua orang.
Demokrasi dalam masyarakat yang tidak tercerahkan yang dipahami sebagai PEMILIHAN BEBAS (dan rahasia) dan berpikir serta berbicara sebebas-bebasnya, cenderung melahirkan pemimpin populis yang pada akhirnya cenderung menjadi tiran. Sebab untuk memilih pemimpin, masyarakat yang belum tercerahkan (yang masih belum mampu berpikir logis) cukup dicekoki dogma, entah itu dogma adat dan yang paling umum AGAMA dan ketika dogma ini sudah merasuk, merekapun segera memakai kacamata kuda.
Karena itulah pemimpin populis banyak kita temui hidup di masyarakat yang masih asing dengan pola pikir logis dan rasional seperti kita. Pemimpin jenis ini memang cocok untuk hidup di tengah masyarakat yang belum tercerahkan, di tengah masyarakat yang masih belum terbiasa berpikir rasional dan logis. Sebab masyarakat seperti ini mudah dikelabui dengan kata-kata besar dan perilaku populis yang menyenangkan, tanpa bisa menyadari kalau sikap itu adalah sebuah usaha dari si pemimpin untuk menutupi ketidakmampuannya.
Masyarakat seperti inilah yang dikritik oleh George Orwell dalam novel fenomenalnya “1984”, novel yang menggambarkan sebuah masyarakat dalam sebuah negara di masa depan yang warganya sudah dicuci otaknya sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi bersikap kritis terhadap apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh pemimpinnya.
“Just like ants, they see the small things, big things they can’t”, kata Orwell di novel itu.
Demokrasi dalam masyarakat seperti ini sama seperti demokrasi yang di Yunani pada zaman Sophisme yang dicerca habis oleh Sokrates (baca www.lintasgayo.com/45575/sophisme-yunani-dan-gayo-masa-kini.html).
Jadi meskipun Budi hardiman sebagaimana dikutip oleh Dedy Saputra E dalam tulisan yang saya komentari ini mengatakan “demokrasi deliberatif dimana keluarnya sebuah peraturan haruslah melibatkan warga negara adalah sebuah keniscayaan”. Tapi dalam masyarakat yang kebebasannya masih didasari oleh Subjektivitas, bukan objektivitas. Alih-alih membawa kebaikan, demokrasi deliberatif malah bisa menciptakan kehancuran.
Sebab yang namanya subjektivitas itu bukan saja berlainan, melainkan bisa bertentangan antara satu orang/kelompok dengan yang lain. Kebebasan berpikir dan berbicara yang dilandasi oleh subjektivitas (kepentigan) ini seringkali mengakibatkan permusuhan.
Referensi :
[1] ENLIGHTENMENT
= fundament of American Democracy = model for a better world.
http://www.studentsfriend.com/sf/part2see/part2-2.html
[2] The American Revolution
http://www.likesbooks.com/france2.html
[3] Grecian Democracy vs. Modern Democracy based on The Enlightenment
http://www.blupete.com/Literature/Essays/BluePete/Democracy.htm
[4] Kant,Immanuel. 1781. THE CRITIQUE OF PURE REASON,
[5] Orwell, George. 1945. Animal Farm, a fairy story. London, Secker and Warburg