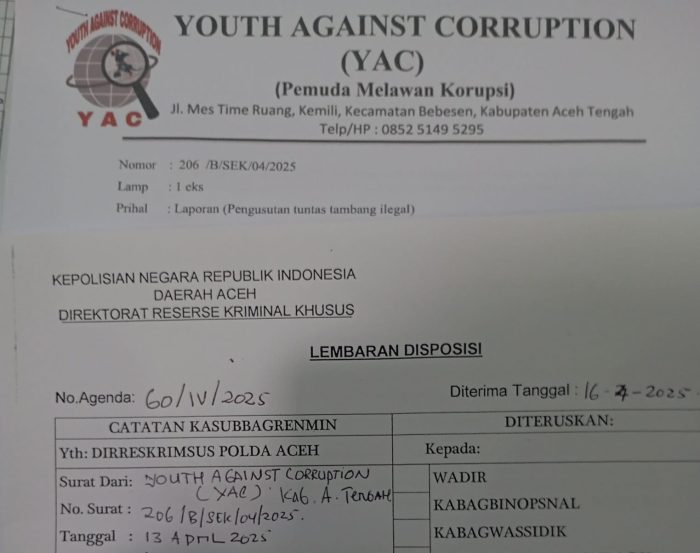Oleh :Ghazali Abbas Adan*
Hebat memang, tinggal dalam teritori regional, tetapi bicaranya global. Kalau memakai istilah kami-kami orang desa; ” Haba lua nanggroe, taloe keu-ieng ngom”. Agaknya ungkapan ndeso (kampung) ini korelatif dengan pernyataan Malik Mahmud yang disebut sebagai Wali Nanggroe dalam sambutannya di majlis memperingati 9 tahun penandatangan MoU Helsinki (15 Agustus 2014), yakni dia berbicara tentang “pasar bebas Asean, masalah dan persaingan global” (The Globe Journal, 15/8/2014).
Menurut pemahaman saya tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Wali Nanggroe sebagaimana dalam UUPA adalah ihwal adat istiadat Aceh yang selaras dengan syari’at Islam dan pemersatu rakyat Aceh dengan karakter tidak partisan, sektarian dan primordial.
Namun sejauh yang saya ikuti dan pantau selama ini, Wali Nanggroe Malik Mahmud, dengan panggilan Paduka Yang Mulia, serta rupa-rupa laqab, yakni Al-Mukarram Maulana, Al-Mudabbir Al-Malik, belum fokus melaksanakan tupoksinya itu.
Berdasarkan nash Quran dan hadis, saya belum mendengar “fatwa” Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tentang adat istiadat Aceh yang selaras dengan syari’at Islam dan harus menjadi pedoman kaum muslimin di Aceh dalam dialektika peradatannya. Demikian pula sebagai pemersatu rakyat Aceh yang heterogen, belum mengeluarkan “fatwa” yang menjadi fondasi dalam interaksi horizontal rakyat yang heterogen dalam teritori Aceh, sehingga dalam aktifitas dan profesi apapun yang dilakoni rakyat Aceh akan senantiasa damai, rukun, tolerans dan saling menghargai. Tidak seperti yang terjadi selama ini, terutama dalam kaitannya dengan kompetisi politik yang melibatkan internal Aceh, pemilukada dan pemilu legislatif, karena ulah gerombolan fasis jahiliyah selalu ada huru-hara, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa. Dalam situasi dan kondisi demikian, seingat saya tidak pernah terdengar suara Malik Mahmud yang disebut sebagai Wali Nanggroe itu. Bahkan terkadang kerap tampil partisan, sektarian dan primordialis. Ini dapat dilihat melalui iklan, spanduk dan baliho, terutama terpampang di kawasan pasisir Aceh.
Sebagai pemersatu rakyat Aceh yang heterogen itu, sejatinya pula melakukan safari ke seluruh zona Aceh, yakni pantai timur, barat dan bagian tengah, niscaya dapat bersilaturahmi, tatap muka dan berdialog dengan berbagai elemen rakyatnya. Terutama di hari baik dan bulan baik, seperti bulan Ramadhan. Tapi faktanya selama ini hanya berkutat di Kota Banda Aceh, atau di seputar teritori tertentu yang kepala pemerintahan dipegang “geng” nya.
Harapan saya ke depan, sesuai dengan tupoksi Wali Nanggroe sebagaimana dalam UUPA, niscaya lebih fokus dan berbuatlah yang itu saja, tidak perlu inprovisasi dan mencampuri yang bukan tupoksinya. Ihwal isu global dan pasar bebas Asean, biarlah urusan Gubernur atau Wakil Gubernur. Wali Nanggroe cukup bicara adat istiadat dan bersungguh-sungguh dan transparan tampil sebagai pemersatu rakyat Aceh yang heterogen, agar dalam event apapun rakyat Aceh tetap hidup aman, damai, rukun, tolerans dan saling menghargai.
Wassalam
Seorang rakyat jelata di Aceh*